Saya pernah bekerja di sebuah tempat yang ramai. Penuh klakson, jadwal rapat, dan orang-orang yang bicara soal target. Setiap pagi, semua bergegas seolah hari itu adalah perlombaan terakhir. Tidak ada yang cukup: tidak waktu, tidak gaji, tidak kelegaan. Hingga suatu hari, saya berhenti. Bukan karena sudah kaya, tetapi karena tubuh dan pikiran saya mulai protes.
Aneh sekali—ketika saya berhenti mengejar, justru beberapa hal yang saya butuhkan datang sendiri. Bukan dari pekerjaan, tapi dari arah yang tak pernah saya perhitungkan.
Seorang tetangga datang membawa sekeranjang buah, katanya panen dari kebun belakang yang tak pernah saya tahu sebelumnya. Seorang teman lama menghubungi untuk menawarkan kerja ringan, cukup dari rumah. Semuanya datang seperti angin yang tahu kapan harus lewat. Dan entah kenapa, saya tidak kaget. Hanya terdiam, seperti sedang diingatkan sesuatu yang pernah saya tahu tapi lama saya abaikan: bahwa rezeki tidak pernah tersesat.
Sebagian orang mengira rezeki seperti burung langka yang harus diburu dengan jaring dan umpan mahal. Maka mereka sibuk merancang strategi, mengepak proposal, menandai peluang. Tidak ada yang salah. Tapi ketika semua itu dilakukan dengan ketegangan, dengan rasa takut kekurangan, dengan meninggalkan waktu-waktu sujud, rasanya ada yang bergeser dalam cara kita memandang hidup.
Rezeki, rupanya, bukan hadiah dari kerja keras semata. Ia juga buah dari ketenangan batin, dari kejujuran yang dirawat, dari tangan yang tidak rakus. Ia datang bukan karena kita paling pintar, tapi karena kita bersedia menerima, meski lewat jalan yang tidak kita minta.
Saya pernah bertanya pada seorang pedagang kecil yang lapaknya tak pernah sepi, padahal ia tak punya iklan dan harganya biasa saja. “Apa rahasianya?” Ia menjawab ringan, “saya tidak ngutang ke rasa serakah.”
Saya tidak sepenuhnya paham maksudnya waktu itu. Tapi semakin ke sini, saya mengerti: rasa serakah bisa membuat kita terus merasa lapar meski meja sudah penuh. Dan ketika hati kita sibuk menagih lebih, kita jadi buta melihat apa yang sebenarnya cukup.
Dalam banyak hal, rezeki datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Kadang ia datang sebagai tawa anak yang sehat. Kadang sebagai waktu tidur yang tenang. Kadang sebagai teman yang jujur. Dan kadang sebagai kehilangan—yang membawa kita pada pemahaman baru tentang makna memiliki.
Ada orang yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan panggilan hidupnya. Ada yang gagal menikah, lalu bertemu pasangan yang betul-betul menjadi rumah. Ada yang jatuh miskin, lalu belajar hidup lebih pelan dan penuh makna. Dalam setiap kehilangan yang kita keluhkan, bisa jadi sedang ada rezeki yang diselipkan.
Rezeki tidak selalu berupa uang. Dan uang tidak selalu rezeki. Kadang ia hanya mampir untuk menguji: akan digunakan untuk apa, dengan cara bagaimana ia diperoleh, dan seberapa besar kita masih ingat untuk bersyukur. Maka tidak heran jika dalam tradisi lama, orang tua kita lebih sering mendoakan rezeki yang halal dan berkah, bukan hanya yang besar.
Kita hidup dalam zaman yang mengukur segalanya dengan angka. Penghasilan, produktivitas, bahkan kebahagiaan. Tapi rezeki tidak bisa dilihat dari angka semata. Ia lebih seperti udara yang bersih—tidak terlihat, tapi terasa. Dan ketika ia hadir, kita akan tahu tanpa perlu diberi tahu.
Jika hari ini engkau merasa letih karena terus mengejar, mungkin bukan karena rezekinya lambat. Mungkin karena engkau berlari terlalu jauh dari tempat ia biasa datang. Sebab sering kali, rezeki tidak datang lewat jalan yang rumit, tapi lewat hal-hal sederhana yang kita lupakan: salat yang khusyuk, senyum yang jujur, sabar yang tidak diumumkan, dan sedekah yang tak dicatat siapa-siapa.
Dan bisa jadi, rezeki yang engkau tunggu itu sedang menunggu engkau kembali. Bukan kembali ke pasar, tapi ke sujud.
Karena pada akhirnya, rezeki tak pernah salah alamat. Ia hanya sedang menunggu rumah yang tenang untuk ia ketuk.

 3 hours ago
1
3 hours ago
1























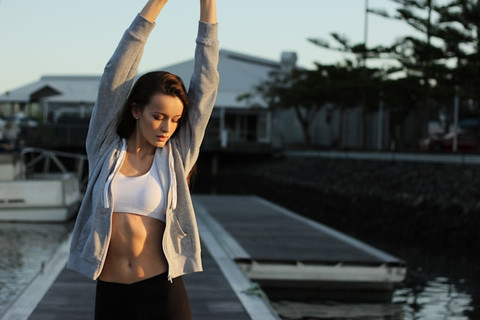





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)









 English (US) ·
English (US) ·