 Gambar dihasilkan oleh AI.
Gambar dihasilkan oleh AI.Waktu saya masih duduk di bangku SMP, sempat ramai tren di kalangan remaja “hitz” saat itu yang disebut skip challenge, atau dikenal juga sebagai pass out challenge. Sesuai namanya, tujuan dari tantangan ini adalah membuat seseorang kehilangan kesadaran. Caranya adalah dengan menekan dada sekuat mungkin selama beberapa waktu, sampai tubuh kekurangan oksigen dan akhirnya pingsan.
Hampir semua remaja saat itu ikut-ikutan tren ini. Bukan cuma di Indonesia, tren skip challenge menyebar secara global melalui sosial media. Saking ramainya, banyak pihak mulai angkat suara soal bahaya dari tantangan ini. Mulai dari media besar seperti BBC, sampai institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada, menulis artikel untuk mengingatkan publik soal risiko serius di balik tren ini. Dan kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada tahun 2019, seorang anak dilaporkan meninggal dunia akibat tantangan serupa yang dikenal sebagai blackout challenge. Tujuannya pun sama, yaitu membuat diri sendiri pingsan.
Pengaruh media sosial memang sangat besar. Ketika ada satu tren fashion yang sedang populer, orang-orang pun berbondong-bondong ikut-ikutan. Begitu juga dengan opini. Kalau ada satu pendapat tentang artis A yang tiba-tiba viral, banyak orang cenderung ikut setuju begitu saja tanpa berpikir panjang atau mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.
 Image by Rosy / Bad Homburg / Germany from Pixabay
Image by Rosy / Bad Homburg / Germany from PixabayDi Indonesia, hal semacam ini pernah terjadi saat kasus Audrey mencuat. Waktu itu, jagat maya ramai dengan tagar #JusticeForAudrey, yang mendukung seorang remaja Pontianak yang mengaku dibully oleh 12 temannya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata cerita itu hanyalah karangan Audrey sendiri. Ia sengaja membuat cerita tersebut demi menarik perhatian publik dan ingin terkenal.
Melihat kembali fenomena-fenomena tadi, ditambah dengan fakta bahwa jumlah pengguna internet terus meningkat dari tahun ke tahun, saya jadi merasa tergelitik untuk menulis artikel ini. Kenapa, di era yang katanya "era terkoneksi", saat semua hal saling terhubung, kita justru semakin seragam dalam cara berpikir?
Bukankah seharusnya kita menjadi lebih beragam dalam sudut pandang dan pemikiran? Kenapa kita malah cenderung mengikuti tren begitu saja, menelan mentah-mentah opini yang sedang viral, dan membiarkan algoritma menentukan apa yang layak kita lihat, pikirkan, atau percayai?
Rasa penasaran saya pun semakin besar. Saya sempat melakukan survei kecil-kecilan di sekitar saya untuk menanyakan satu hal sederhana: "Apa hobi kamu?" Kebetulan saya lahir di generasi Z (Gen Z), dan dari pengamatan saya, kebanyakan dari mereka justru kesulitan menjawab pertanyaan itu. Ada yang bilang hobinya adalah “mengikuti hal yang seru”, atau bahkan tidak sedikit yang menjawab, “nggak tahu.”
 Image by Mohamed Hassan from Pixabay
Image by Mohamed Hassan from PixabayJujur, ini benar-benar menjadi alarm buat saya. Kenapa sekarang orang-orang jadi sulit menemukan hobi? Ke mana perginya diri kita yang dulu? Diri yang bisa betah main tanah berjam-jam, atau yang kalau ditanya soal hobi langsung punya seribu jawaban mulai dari main bola, membaca, menggambar, dan banyak lagi?
Setelah melakukan riset kecil-kecilan, saya mulai menyadari bahwa salah satu penyebab mengapa manusia sekarang cenderung memiliki tren, cara berpikir, bahkan tindakan yang seragam adalah karena algoritma media sosial yang kini sangat berperan besar dalam membentuk preferensi kita.
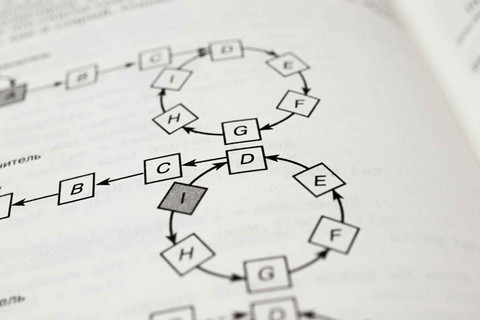 Photo by Андрей Сизов on Unsplash
Photo by Андрей Сизов on UnsplashAlgoritma dirancang untuk menunjukkan hal-hal yang dianggap relevan, dalam arti yang paling sederhana: sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah kita sukai, klik, atau habiskan waktu menonton. Akibatnya, kita terus-menerus disuguhi konten yang itu-itu saja. Tanpa sadar, kita hidup dalam gelembung yang dipersonalisasi. Sekilas, semua itu terlihat seperti pilihan kita sendiri, padahal sebenarnya sudah dikurasi oleh sistem.
Inilah yang membuat banyak orang cenderung punya referensi yang sama, selera yang mirip, hingga opini yang seragam. Bukan karena kita tidak mampu berpikir sendiri, tetapi karena ruang untuk mengeksplorasi hal-hal yang berbeda menjadi semakin sempit. Algoritma membuat semuanya terasa aman, nyaman, dan familiar. Tapi justru di situlah akar dari homogenitas mulai tumbuh.
 Photo by おにぎり on Unsplash
Photo by おにぎり on UnsplashHomogenitas di media sosial dan internet juga menjadi salah satu alasan mengapa, di era sekarang, menemukan hobi terasa jauh lebih berat. Ini karena algoritma perlahan-lahan mengaburkan apa yang sebenarnya kita sukai. Misalnya, ketika di media sosial sedang ramai tren terjun payung, banyak orang jadi ikut mencoba.
Atau seperti sekarang, saat olahraga padel sedang viral, orang-orang pun berbondong-bondong mengikuti tren itu. Apakah hal tersebut buruk? Tentu tidak. Justru bagus jika seseorang jadi semangat berolahraga setelah melihat orang lain di internet yang juga aktif bergerak.
Namun masalahnya muncul ketika kita tidak lagi tahu apa yang benar-benar kita sukai. Kita hanya mengeksplorasi hal-hal yang muncul di FYP atau timeline, tanpa sadar bahwa di luar sana masih banyak hal menarik yang bisa dicoba tanpa harus menunggu algoritma menampilkannya terlebih dahulu.
 Photo by Jason Hogan on Unsplash
Photo by Jason Hogan on UnsplashAkhirnya, artikel ini adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk menolak menjadi manusia yang homogen. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sama, tapi untuk menciptakan berbagai macam budaya, cara berpikir, dan hobi. Menjadi berbeda, punya pandangan sendiri, dan menikmati keragaman jauh lebih menyenangkan dibanding hidup di dunia yang dicetak rata oleh algoritma.
Coba taruh dulu gawaimu. Matikan internet sejenak. Ambil secarik kertas, dan tuliskan: hal apa yang dulu pernah sangat ingin dicoba oleh dirimu yang kecil? Mungkin kamu akan terkejut melihat jawaban jujur yang muncul.
Gunakan internet dengan tujuan. Jelajahi dengan kesadaran. Jangan mau digerakkan sepenuhnya oleh algoritma. Karena pada akhirnya, kamulah yang seharusnya memegang kendali. Bukan algoritma. Kamu adalah rajanya, bukan pengikutnya.

 1 month ago
3
1 month ago
3




















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·