 Photo by Tim Gouw from Pexels: https://www.pexels.com/photo/women-in-cafe-240223/
Photo by Tim Gouw from Pexels: https://www.pexels.com/photo/women-in-cafe-240223/Ungkapan seperti ini bukan hal asing di kalangan Gen Z yang hidup di kota-kota besar Indonesia.
Dalam dunia yang kian serba cepat, banyak anak muda yang merasa asing terhadap dirinya sendiri. Mereka bekerja, bersosialisasi, dan terus “berprogres”. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan eksistensial: Siapa aku sebenarnya? Apakah aku sedang menjalani hidupku sendiri, atau sekadar menunaikan ekspektasi sosial?
Dalam kerangka sosiologi modern, fenomena ini telah lama dikaji oleh Anthony Giddens (1991) melalui konsep reflexive self. Menurut Giddens, di era modernitas lanjut (late modernity), identitas bukan lagi sesuatu yang diwariskan atau bersifat tetap. Identitas menjadi sebuah proyek reflektif yang harus dibentuk dan dikurasi secara terus-menerus oleh individu.
“The self is seen as a reflexive project, for which the individual is responsible. We are, not what we are, but what we make of ourselves.” — Giddens, Modernity and Self-Identity (1991)Artinya, setiap anak muda hari ini dipaksa untuk “menjadi seseorang” dalam dunia yang menawarkan terlalu banyak pilihan, tapi minim stabilitas.
Kota: Ruang Penuh Peluang, Tapi Juga Tekanan
Dalam studi sosiologi urban, kota seringkali dipandang sebagai arena mobilitas sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, kota juga menghadirkan tuntutan harus kompetitif, harus tampil, harus punya “nilai jual” pribadi. Lingkungan perkotaan yang cair (liquid) menyebabkan identitas sosial individu turut menjadi cair, tidak menetap, mudah bergeser, dan rawan kehilangan makna.
Seiring dengan berkurangnya keterikatan komunal (komunitas lokal, tradisi, dan adat), individu semakin berjarak dari sumber-sumber identitas tradisional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Giddens (1991):
“Modernity breaks down the protective framework of the small community and of tradition, replacing them with much larger, impersonal organisations.” — Giddens, Modernity and Self-Identity (1991)Kita tidak lagi tumbuh bersama sistem nilai kolektif yang kuat. Sebaliknya, kita berpindah-pindah tempat tinggal, bekerja kontrak, berinteraksi secara digital. Akibatnya, rasa keterhubungan (connectedness) terhadap lingkungan sekitar menjadi rapuh.
Gaya Hidup: Identitas Melalui Konsumsi?
Giddens juga mengingatkan bahwa dalam masyarakat modern, gaya hidup (lifestyle choices) menjadi penanda identitas utama. Dalam dunia Gen Z, ini tampak dari keputusan-keputusan kecil hingga besar: memilih pakaian, membeli gadget, tinggal di rumah susun atau apartemen, hingga memilih platform media sosial untuk menampilkan diri.
Namun, semua ini tidak netral. Butuh modal, entah itu ekonomi, sosial, maupun kultural. Maka tidak heran, tekanan untuk “menjadi versi terbaik dari diri sendiri” justru menimbulkan alienasi baru.
Refleksi: Apa Yang Bisa Dilakukan?
Di tengah tuntutan untuk selalu tampil “tahu diri”, “tahu tujuan”, dan “tahu arah”, wajar jika banyak anak muda justru merasa kehilangan arah.
Namun, penting untuk menyadari bahwa krisis ini bukan hanya bersifat personal, melainkan struktural dan sosial. Keresahan kita adalah bagian dari dinamika masyarakat modern yang bergerak cepat, tidak stabil, dan cenderung individualistis.
Menemukan diri dalam lanskap sosial hari ini bukan soal menemukan “jawaban final”, tapi justru soal menyadari bahwa pencarian itu sendiri sah untuk dijalani dan kita tidak sendirian.

 1 month ago
1
1 month ago
1
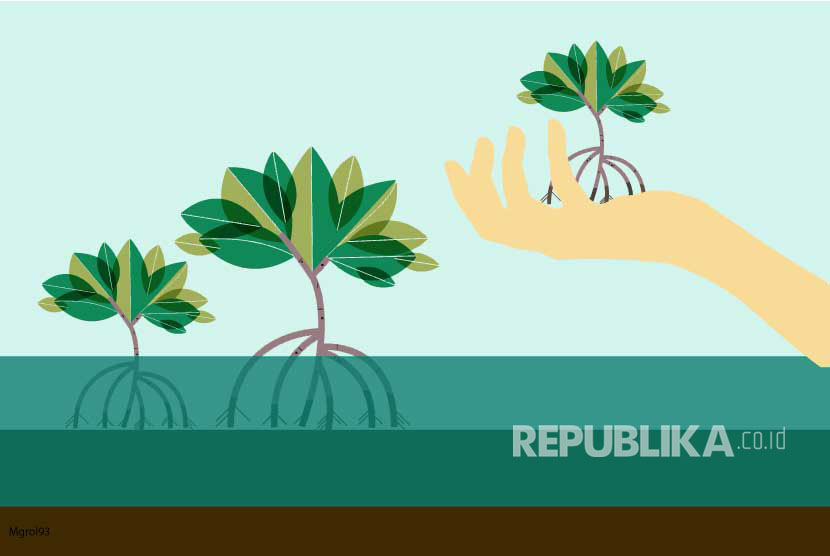
,x_140,y_26/01k20xdqxn9x7qssnyrvjvbchz.jpg)


















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303781/original/072379000_1754124524-Screenshot_2025-08-02_150945.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4104946/original/042371200_1659067441-nathana-reboucas-c4aT8MfEzdw-unsplash.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·