 ilustrasi ketimpangan pendidikan,chatGpt.com
ilustrasi ketimpangan pendidikan,chatGpt.comDi mata kita, sekolah adalah jalan paling sah menuju masa depan yang lebih baik. Tempat di mana kerja keras dihargai, di mana anak-anak dari mana pun—kaya atau miskin—berdiri di garis start yang sama dan berlari menuju pintu kesuksesan. Tapi benarkah semuanya seadil itu?
Dalam praktiknya, mimpi meritokrasi di dunia pendidikan Indonesia sering kali terbentur oleh satu kenyataan pahit: bukan cuma kerja keras yang menentukan, tapi juga di keluarga seperti apa kita dilahirkan.
Ketika Kamera Menyorot Momen Bahagia, Tapi Tak Menyentuh Akar Masalah
Belum lama ini, media sosial dipenuhi video-video yang menyentuh hati. Para rektor universitas negeri datang mengetuk pintu rumah-rumah sederhana, memberi kabar bahagia bahwa anak dari keluarga prasejahtera berhasil masuk kampus bergengsi. Tangis haru pecah. Rektor tersenyum. Kamera merekam. Media menyebarkan.
Momen ini seolah menyampaikan pesan: “lihat, siapa pun bisa sukses asalkan mau berjuang”.
Namun, kisah-kisah seperti ini hanya mewakili 0,01 % dari total 426.449 mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025. Artinya, narasi yang dibangun adalah pengecualian yang dijadikan seolah-olah norma.
Sementara itu, ribuan anak lain dengan mimpi yang sama gagal menembus gerbang kampus impian bukan karena malas, tapi karena sistem yang tidak berpihak.
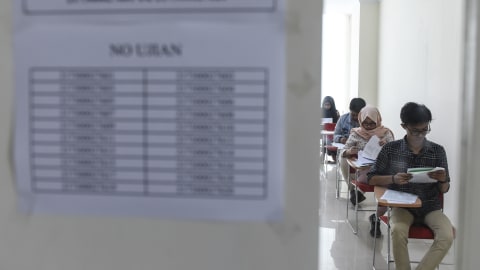 Ilustrasi ujian masuk PTN. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi ujian masuk PTN. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ABukti Bahwa Peluang Tak Pernah Sama
Menurut BPS (2023), hanya 10,15% anak usia 19–24 tahun dari kelompok termiskin yang bisa masuk pendidikan tinggi. Sementara dari kelompok terkaya, angkanya menyentuh 42,31%. Jadi, anak dari keluarga kaya punya peluang 4x lipat lebih besar untuk kuliah, dibandingkan anak dari keluarga miskin.
Ini bukan hanya soal uang. Ini soal akses terhadap fasilitas, lingkungan belajar yang kondusif, bimbingan belajar, koneksi orang tua, dan bahkan kesehatan mental yang stabil—semua itu lebih mungkin dimiliki mereka yang “lahir di keluarga yang tepat”.
Mitos Meritokrasi di Ruang Kelas
Kita suka percaya bahwa nilai rapor, skor ujian, dan IPK adalah indikator murni dari kecerdasan dan kerja keras. Padahal, semua itu juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus belajar di rumah yang tidak nyaman, tanpa internet stabil, tanpa les privat, sambil membantu orang tua bekerja. Lalu mereka dinilai sama dengan anak-anak yang punya semua fasilitas sejak lahir.
Apakah itu adil?
Di sinilah mimpi meritokrasi goyah. Karena kerja keras memang penting, tapi tidak semua orang punya peluang yang sama untuk bekerja keras dengan maksimal.
Pendidikan Harus Jadi Alat Pemerataan, Bukan Pengukuh Ketimpangan
Jika sekolah hanya menjadi alat untuk menyaring siapa yang sejak awal sudah punya privilese, maka pendidikan kehilangan makna dasarnya. Kita butuh sistem yang tidak cuma menilai hasil akhir, tapi juga mengakui latar belakang, memberi ruang afirmatif, dan memastikan bahwa setiap anak—apa pun latar belakangnya—benar-benar punya kesempatan yang setara.
Sampai hari itu tiba, mimpi meritokrasi akan tetap jadi milik mereka yang lahir di tempat yang tepat.

 3 weeks ago
1
3 weeks ago
1


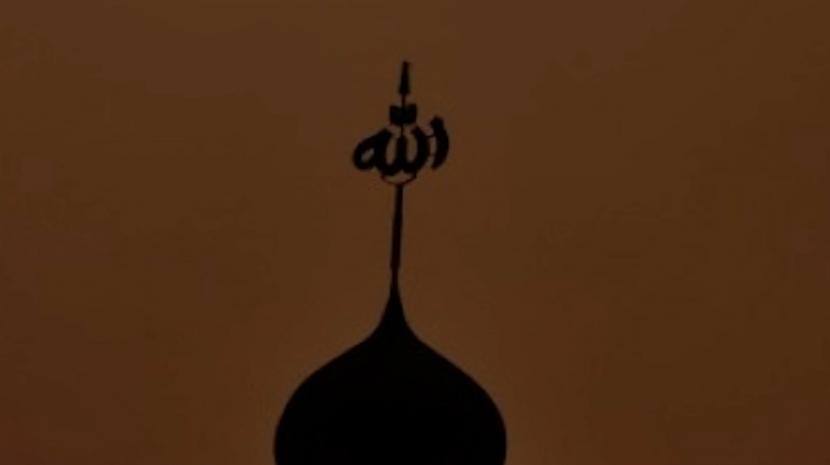













,x_140,y_26/01k37j5tzbp0v55agefznjtkvz.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·