 Ari J. Palawi
Ari J. Palawi
Humaniora | 2025-08-23 09:39:53
 Literatur Sejarah Seni Lintas Bangsa (2025)
Literatur Sejarah Seni Lintas Bangsa (2025)
Halaman Kosong dan Ketakutan yang Wajar
Saya sering mendengar keluhan: “Aku buntu, tidak bisa menulis skripsi. Ideku berantakan, kepalaku penuh, tapi tanganku kaku.”
Itu wajar. Bahkan penulis besar pun pernah—dan masih—berdiri di depan halaman kosong dengan perasaan kalah. Menulis sering dianggap bakat yang turun dari langit, padahal ia lebih mirip otot: bisa lemah, bisa kuat, tergantung dilatih atau tidak.
Masalahnya, kita sering menunggu “mood” datang. Padahal menulis jarang dimulai dari inspirasi agung. Ia biasanya lahir dari yang sepele: sebuah catatan di HP, coretan di kertas ujian, atau pertanyaan iseng di kepala: “Kenapa begini?” Dari yang remeh itu, kata-kata perlahan menemukan bentuknya.
Menulis memang bisa menyakitkan, tapi juga bisa menyenangkan. Yang perlu diubah adalah cara kita memandangnya: bukan sebagai beban yang harus sempurna sejak awal, melainkan sebagai perjalanan kecil yang bisa dinikmati dari kalimat pertama.
Kata: Bahan Baku Semesta
Kata adalah bahan baku menulis, seperti atom bagi semesta. Kita sering meremehkan kata, menganggapnya sekadar “alat komunikasi”—sesuatu yang keluar begitu saja saat bicara. Padahal kata lebih dari itu: ia adalah medium berpikir.
- Dengan kata, kita mengingat. Ingatan tentang pengalaman masa lalu baru terasa utuh ketika bisa kita ceritakan.
- Dengan kata, kita membangun argumen. Tanpa kata, ide hanya gumpalan samar di kepala.
- Dengan kata, kita mengajukan klaim akademik. Skripsi tidak lahir dari ilham semata, melainkan dari kata-kata yang dipilih, disusun, dan dipertanggungjawabkan.
Menulis, dengan demikian, bukan soal menyalin informasi yang sudah ada, melainkan melatih otak untuk berpikir secara teratur. Menulis membuat kita menyeleksi apa yang penting, menyingkirkan yang berlebihan, dan menemukan hubungan antaride.
Itulah sebabnya, meski bentuknya bisa berbeda-beda—skripsi, makalah, cerpen, pidato—semuanya berakar pada satu keterampilan yang sama: keterampilan menulis sebagai keterampilan berpikir.
Dan di sinilah letak keindahan (sekaligus tantangan): ketika kita menulis, sebenarnya kita tidak hanya membuat teks. Kita sedang membentuk cara kita memahami dunia.
Dari Coretan ke Struktur
Tak seorang pun memulai skripsi dari Bab 1 yang mulus. Semua penulis—entah ia mahasiswa tingkat akhir, jurnalis, atau novelis—selalu memulai dari coretan. Ide acak di kertas buram, potongan kutipan dari buku, catatan tangan di sela kelas, bahkan catatan kecil di ponsel. Dari kepingan inilah perlahan terbentuk sesuatu yang lebih besar.
Struktur adalah peta. Skripsi tanpa struktur hanyalah curhat panjang yang membingungkan. Cerpen tanpa struktur hanyalah mimpi samar yang tidak bisa dinikmati pembaca. Struktur bukan musuh kreativitas, melainkan pegangan agar ide yang liar tidak hilang arah.
Di sinilah latihan menulis menjadi penting. Dengan menulis, kita belajar mengelompokkan gagasan: mana yang harus jadi pembuka, mana yang pantas masuk isi, dan mana yang lebih tepat menjadi kesimpulan. Pola dasar ini bisa sederhana—awal, tengah, akhir—tetapi dari kesederhanaan itulah muncul kerangka yang bisa ditelusuri.
Analoginya seperti jalan setapak. Kalau kita tahu jalurnya, orang lain bisa mengikuti tanpa tersesat. Dan begitulah seharusnya tulisan bekerja: tidak hanya memuat isi kepala kita, tapi juga mengarahkan pembaca untuk ikut berpikir bersama.
Dari coretan menuju struktur, kita sedang belajar menata bukan hanya tulisan, tapi juga cara berpikir kita sendiri.
Dari Teknik ke Suara
Setelah kita terbiasa menulis dan menguasai struktur dasar, kita menyadari sesuatu: menulis bukan hanya soal benar atau salah dalam tata bahasa. Kalau menulis hanya diukur dari kaidah EYD atau aturan sitasi, hasilnya mungkin rapi, tapi hambar.
Yang membuat tulisan hidup adalah suara.
Suara akademik berbeda dengan suara sastra. Suara skripsi menuntut argumen yang sistematis, rujukan yang sahih, dan bahasa yang terukur. Tetapi bukan berarti skripsi harus kering seperti laporan mesin. Justru skripsi yang baik tetap menampakkan “posisi penulis” di balik teori dan data—apakah ia yakin, ragu, atau kritis terhadap sumber yang dikutip.
Suara sastra lain lagi. Ia boleh emosional, metaforis, bahkan melodius, tetapi tetap harus terikat pada alur. Cerpen yang baik bukan sekadar curahan hati, melainkan suara batin yang ditata agar pembaca ikut merasakan denyutnya.
Inilah keindahan menulis: teknik bisa dipelajari, tapi suara adalah identitas. Dan identitas itu lahir dari perjalanan, dari pengalaman personal, dari keberanian untuk menyatakan diri.
Menulis dengan suara sendiri membuat teks terasa otentik, bukan sekadar kumpulan kutipan atau kalimat generik. Ia menjadi tanda bahwa di balik halaman itu ada manusia nyata yang berpikir, merasa, dan berjuang.
Menulis Bisa Jadi Apa Saja
Di titik ini kita sadar: keterampilan menulis tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah keterampilan lintas-genre, bisa menembus batas antara akademik, sastra, maupun komunikasi sehari-hari.
- Catatan harian bisa bertransformasi menjadi esai reflektif yang matang.
- Observasi lapangan bisa disusun menjadi artikel ilmiah yang teruji.
- Pertanyaan sederhana, yang awalnya hanya keresahan pribadi, bisa berkembang menjadi tesis yang serius.
- Curhat pribadi bisa dipoles menjadi puisi yang menyentuh banyak orang.
Menulis, dengan kata lain, adalah kemampuan yang lentur. Seperti air yang mengambil bentuk wadahnya, ia menyesuaikan dengan ruang yang ditempatinya: skripsi, cerpen, pidato, atau bahkan sekadar caption media sosial.
Inilah alasan mengapa menulis begitu penting dipelajari. Ia bukan sekadar bekal untuk menyelesaikan kuliah, tetapi juga keterampilan hidup. Mahasiswa desa yang menulis laporan penelitian berangkat dari akar yang sama dengan penulis kota yang membuat konten daring. Keduanya sedang melatih kejelasan berpikir, keberanian menyampaikan, dan kreativitas dalam mengolah kata.
Dan menariknya, ketika kita bisa menulis untuk berbagai ruang, kita juga belajar beradaptasi. Adaptasi inilah yang membuat menulis tidak pernah kaku. Ia bisa menjadi sarana akademik yang serius, sekaligus sarana ekspresi diri yang cair.
AI Masuk: Antara Godaan dan Manfaat
Kita hidup di era yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika dulu mahasiswa harus menghabiskan waktu berminggu-minggu di perpustakaan untuk mengutip literatur, kini dalam hitungan detik ChatGPT dan “saudara-saudaranya” bisa menyajikan ringkasan teori, bahkan kerangka tulisan.
Maka wajar jika banyak yang tergoda: “Untuk apa repot menulis skripsi kalau mesin bisa melakukannya?”
Saya tidak menutup mata: AI memang berguna. Ia bisa:
- Merangkum teori dengan cepat, sehingga kita tidak tenggelam dalam tumpukan bacaan.
- Menyusun kerangka berpikir yang membantu kita melihat arah.
- Menawarkan variasi gaya bahasa yang bisa memperkaya ekspresi.
Faktanya, AI tidak punya pengalaman. Ia tidak pernah cemas menunggu dosen pembimbing yang menunda bimbingan. Ia tidak pernah merasa lapar saat mengetik dini hari dengan mata setengah tertutup. Ia tidak pernah menanggung rasa gagal, lalu bangkit dengan sisa energi terakhir. Tulisan yang dihasilkan AI tanpa keterlibatan penulis hanyalah teks tanpa jiwa. Indah tapi hampa. Lengkap tapi kosong.
Pertanyaannya yang mendasar bukanlah “apakah boleh menggunakan AI?”, melainkan: bagaimana kita menggunakannya dengan bijak? Di sinilah letak etika sekaligus peluang: AI bisa jadi godaan untuk jalan pintas, tetapi juga bisa menjadi manfaat besar jika diperlakukan sebagai alat, bukan pengganti.
Human Intelligence: Keseimbangan yang Hakiki
Di tengah derasnya arus AI, kita sering lupa bahwa yang membuat tulisan hidup bukanlah algoritma, melainkan Human Intelligence (HI). AI bisa cepat, rapi, bahkan mengejutkan. Tetapi HI membawa sesuatu yang tak tergantikan: keberanian, intuisi, dan pengalaman hidup.
HI adalah:
- Keberanian berpikir kritis – berani bertanya, meragukan, dan menantang jawaban yang terasa terlalu gampang.
- Kepekaan membaca konteks – tahu kapan sebuah teori relevan, dan kapan ia sekadar jargon kosong.
- Intuisi menghadapi data yang tidak lengkap – kemampuan mengambil keputusan meski bukti tidak sempurna.
- Keberanian mengekspresikan pengalaman pribadi – sesuatu yang membuat tulisan terasa otentik, bukan sekadar kutipan bersusun.
AI bisa menyodorkan ribuan kutipan, tetapi HI-lah yang memilih mana yang layak dijadikan landasan argumen. AI bisa membuat kalimat indah, tetapi HI-lah yang menyuntikkan makna yang hanya bisa lahir dari pengalaman nyata. AI bisa memandu arah, tetapi HI-lah yang benar-benar melangkah, dengan segala risiko dan ketidakpastian.
Inilah keseimbangan yang etis: AI sebagai alat bantu, HI sebagai pusat kendali. Tanpa HI, tulisan hanya jadi mesi...

 6 hours ago
2
6 hours ago
2

















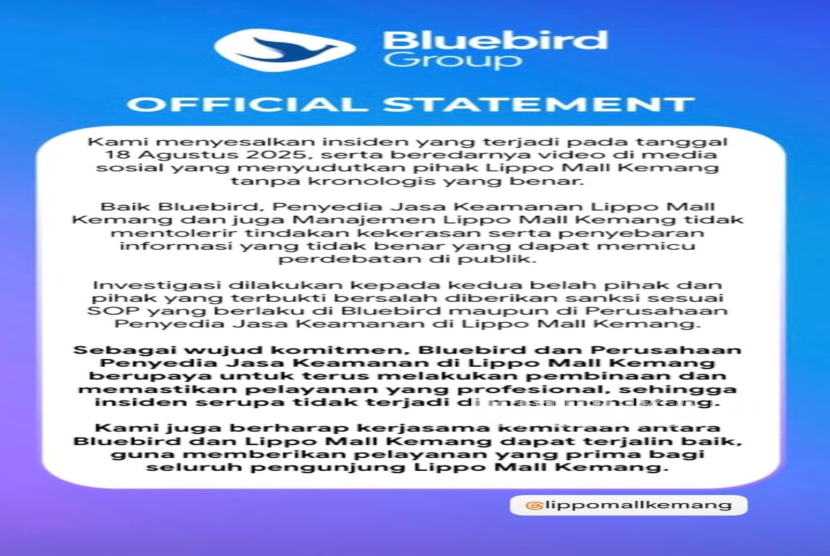


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·