Jakarta (ANTARA) - Dalam diskursus publik, sebagian masyarakat menganggap kebijakan pajak pejabat yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk privilese yang mengistimewakan pejabat negara, dan seolah-olah menjadi terbebas dari kewajiban membayar pajak.
Narasi yang muncul di ruang publik pun sering kali bersifat simplistis: "Mengapa rakyat kecil dipotong pajaknya, sementara pajak pejabat justru dibayarkan negara?"
Pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan publik atas keadilan sistem perpajakan, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi dan beban fiskal negara.
Jika ditelisik lebih jauh, polemik ini bukan semata soal hilangnya penerimaan negara. Secara teknis, pajak pejabat yang ditanggung pemerintah tetap masuk ke kas negara. Hanya alur pembayarannya yang berbeda, yakni melalui pos belanja khusus dalam APBN. Artinya, negara tidak mengalami revenue loss.
Namun, problem yang mengemuka lebih terkait dengan persepsi keadilan. Rakyat melihat adanya perbedaan perlakuan: masyarakat umum harus rela menerima gaji bersih setelah dipotong pajak, sedangkan pejabat tetap menikmati gaji penuh tanpa pengurangan.
Konteks ekonomi Indonesia semakin memperkuat sensitivitas isu ini. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa rasio pajak Indonesia pada 2024 hanya mencapai 10,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang berada di kisaran 33 persen.
Di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini) Indonesia pada Maret 2024 berada di angka 0,388, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pajak bagi pejabat negara menjadi sorotan tajam karena dianggap bertolak belakang dengan semangat pemerataan.
Selain itu, belanja pegawai pemerintah pusat pada 2024 mencapai Rp257,2 triliun atau sekitar 8,6 persen dari total belanja negara. Dari angka tersebut, sebagian dialokasikan untuk skema pajak DTP.
Meskipun porsi DTP relatif kecil dibandingkan total belanja pegawai, simbolismenya besar: publik menilai negara memberikan “fasilitas fiskal” bagi pejabat, sementara masyarakat umum harus berjuang di tengah tekanan harga dan kewajiban pajak yang tidak bisa dihindari.
Dengan demikian, persoalan utama bukanlah pada hilangnya penerimaan negara akibat skema DTP, melainkan pada legitimasi moral dan rasa keadilan yang muncul di ruang publik.
Tulisan ini akan mengurai lebih dalam bagaimana mekanisme pajak pejabat DTP bekerja, logika fiskal yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kebijakan ini dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan pajak yang menjadi fondasi legitimasi sistem perpajakan modern.
Baca juga: DJP siapkan strategi kejar target pajak Rp2.357 triliun pada 2026
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.













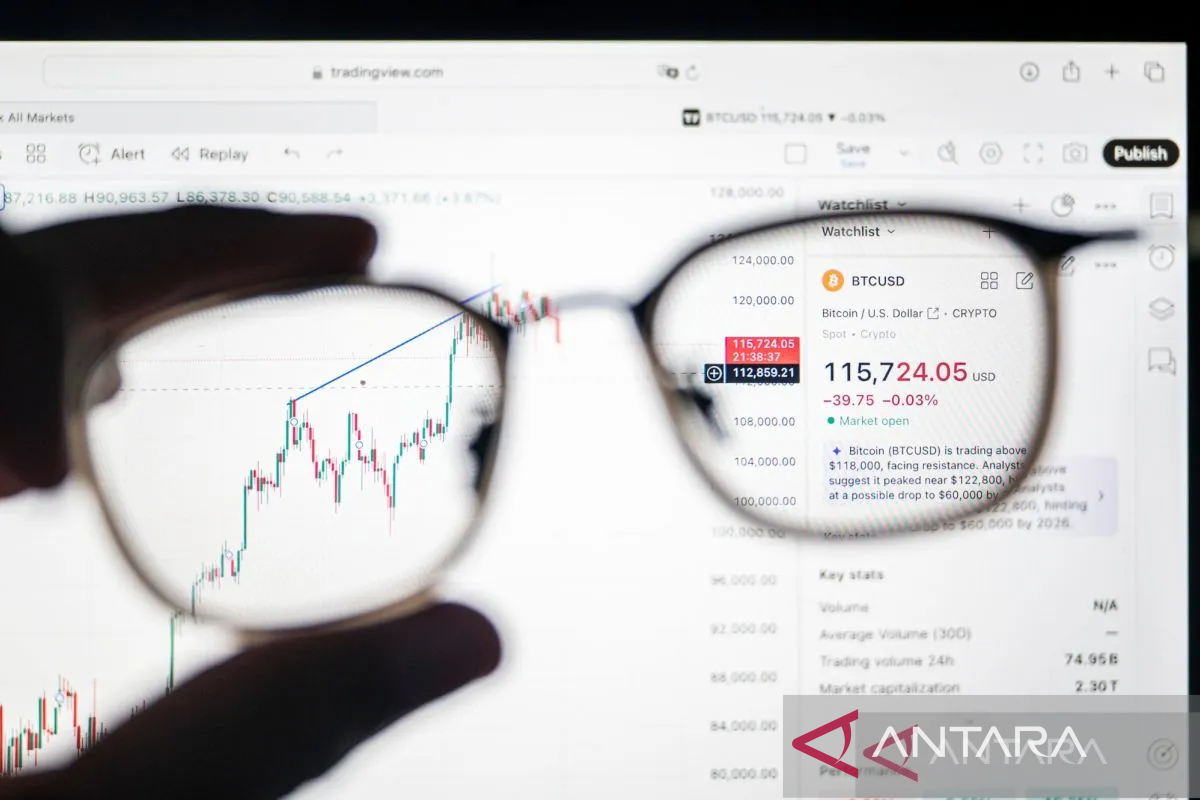






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·