 Badrut Tamam
Badrut Tamam
Eduaksi | 2025-08-18 05:25:12

Oleh : Arsinah, M.SI
Dosen FTIK UINSI Samarinda, Ketua II PC Muslimat NU Samarinda.
Bumi kita sedang menjerit—pelan tapi pasti.
Ia kelelahan memikul beban peradaban yang terus tumbuh tanpa jeda. Udara yang dulu segar kini tercekik oleh polusi. Hutan-hutan yang dahulu rimbun kini tinggal bayang, digantikan beton dan debu. Sampah plastik tak hanya mencemari kota besar, tetapi juga menyusup ke sungai, laut, bahkan hingga ke sela-sela desa terpencil.
Kita hidup di tengah gegap gempita modernisasi, di tengah pembangunan yang tak pernah mengenal istirahat. Namun di balik kemajuan itu, ada satu kenyataan pahit yang tak bisa kita abaikan: bumi, rumah kita bersama, sedang terluka. Dan luka itu, disadari atau tidak, sebagian besar ditorehkan oleh tangan manusia.
Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi menggugah:
“Apa yang bisa saya lakukan?”
Seringkali kita merasa terlalu kecil untuk membuat perubahan. Seolah menjaga bumi adalah urusan para ilmuwan, aktivis, atau pemangku kebijakan. Padahal, tidak demikian.
Menjaga bumi bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana:
– Tidak membuang sampah sembarangan.
– Membatasi konsumsi berlebih.
– Membiasakan diri mencintai alam, sebagaimana kita mencintai hidup itu sendiri.
Dan yang paling mendasar: dari iman yang hidup dalam hati.
Sebab dalam keimanan yang utuh, merawat bumi bukan sekadar pilihan. Ia adalah bagian dari ibadah, bagian dari syukur, dan bagian dari cinta kita kepada Sang Pencipta.
-
Ketika Sujud Menyentuh Tanah: Cerita dari Samarinda
Di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda, berdiri sebuah pondok pesantren yang mungkin luput dari sorotan publik, tetapi menyimpan makna besar dalam geraknya. Namanya Pondok Pesantren Syekh Chona Kholil. Di balik pagar sederhana dan kebun yang rindang, tumbuh semangat luar biasa: menyatukan spiritualitas dengan kepedulian terhadap lingkungan.
Di pesantren ini, ibadah tak berhenti di atas sajadah. Ia menjalar hingga ke kebun, ke sungai, ke tong kompos, dan ke akar-akar pohon yang baru ditanam. Para santri tidak hanya menghafal ayat-ayat suci, tapi juga menanam sayur, mengelola sampah, membuat sabun dari minyak bekas, dan membersihkan lingkungan bersama warga sekitar.
Sebab bagi mereka, mencintai alam adalah bentuk paling nyata dari mencintai Allah.
Alam bukan benda mati—ia adalah ayat-ayat Tuhan yang bisa dibaca, dirasa, dan dijaga.
Apa yang melandasi praktik ini? Apa yang menggerakkan pesantren ini menjadikan ekologi sebagai bagian dari kurikulum keimanan?
Untuk memahaminya, kita perlu menyelami satu konsep penting: ekoteologi.
-
Ekoteologi: Ketika Iman Menyapa Alam
Ekoteologi adalah titik temu antara dua kekuatan besar: ekologi (ilmu tentang hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya) dan teologi (ilmu tentang ketuhanan dan keyakinan). Dari persinggungan ini lahir sebuah kesadaran baru—bahwa merawat bumi bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga panggilan spiritual.
Dalam Islam, konsep ini telah tertanam sejak lama. Kita mengenal istilah khalifah fil ardh—manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebuah mandat yang tidak hanya mulia, tapi juga penuh tanggung jawab. Menjadi khalifah berarti menjaga, bukan mengeksploitasi.
Allah SWT berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”
(QS. Ar-Rum: 41)
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakan darinya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dari ayat dan hadis ini, kita belajar bahwa Islam memandang alam sebagai amanah, bukan sekadar sumber daya. Bahkan menanam satu pohon pun dinilai sebagai sedekah. Maka merusak alam, sadar atau tidak, adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keimanan.
Ekoteologi Islam berpijak pada tiga pilar utama:
1. Tauhid – bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah.
2. Rahmah – kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup.
3. Amanah – bumi adalah titipan, yang wajib dijaga dan dilestarikan.
Ketiga hal ini menjadi pilar ekoteologi Islam, bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar tindakan ekologis, melainkan wujud keimanan. Tauhid menegaskan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati; Rahmah mendorong kasih sayang terhadap semua makhluk; dan Amanah menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas kelestarian bumi sebagai titipan Ilahi.
-
KH Cholil Nafis memandang tindakan menjaga lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bagian dari iman. Semua praktik konservasi—seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghematan energi, dan pelestarian satwa—mesti dianggap sebagai bentuk ibadah serta tanggung jawab umat sebagai khalifah di bumi. Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI di bawah kepemimpinannya memberikan kerangka hukum syariah bagi umat untuk aktif merawat bumi dan menghindari kerusakan ekologis.
Gagasan ekoteologi juga hidup dalam berbagai tradisi agama. Banyak pemikir lintas iman mengungkapkan pesan serupa.
Seyyed Hossein Nasr, filsuf Muslim, dalam bukunya Religion and the Order of Nature, menyatakan bahwa krisis ekologi muncul karena manusia modern memisahkan spiritualitas dari alam. Padahal alam adalah cermin kehadiran Tuhan—ayat-ayat kauniyah yang harus direnungi.
Thomas Berry, imam Katolik dan ekolog spiritual, menulis tentang The Great Work—konsep bahwa umat manusia memiliki tugas spiritual untuk menyembuhkan bumi, bukan sekadar menggunakannya.
Dua pemikir, dua agama, tapi satu pesan:
Krisis lingkungan adalah krisis spiritual.
-
Ketika Santri Belajar dari Tanah
Di Pesantren Syekh Chona Kholil, pelajaran tentang bumi tak disampaikan lewat buku tebal atau ceramah panjang. Nilai-nilai ekoteologi tumbuh langsung dari tanah—melalui tangan yang kotor oleh lumpur, kaki yang menjejak sawah, dan hati yang diajak memahami alam sebagai bagian dari dzikir.
Di sana, para santri belajar bahwa mencangkul bisa menjadi ibadah, menyiram tanaman adalah bentuk syukur, dan memungut sampah adalah jalan menuju taqwa.
Ilmu tentang alam tidak hanya dipelajari, tetapi dihidupi—dalam irama harian yang jujur, sederhana, dan penuh makna.
1. Berkebun: Belajar dari Benih
Setiap santri merawat petak kebunnya sendiri. Mereka menanam kangkung, bayam, cabai, dan terong—semuanya secara alami, tanpa pestisida.
Pupuknya? Dari kompos hasil olahan sampah dapur pondok.
Namun kebun ini lebih dari sekadar ladang sayur. Ia menjadi ruang belajar kehidupan: tentang kesabaran, ketelatenan, dan keyakinan bahwa rezeki selalu datang melalui proses.
Saat tunas mungil muncul dari tanah kering, para santri melihat keajaiban. Dari situ lahir rasa tunduk yang dalam—bahwa dari tanah yang tandus pun, Allah bisa menumbuhkan kehidupan.
2. Mengelola Sampah dengan Cinta
Di pondok ini, sampah tidak dibuang sembarangan. Sejak awal, santri diajarkan memilah:
– Organik menjadi pupuk.
– Non-organik dibersihkan, dikreasikan ulang.
– Minyak bekas pun disulap menjadi sabun ramah lingkungan.
Mereka tumbuh dengan kesadaran: sampah bukan akhir, tapi awal dari kebermanfaatan baru.
3. Jumat Bersih: Gotong Royong dan Menanam Harapan
Setiap Jumat pagi, santri dan ustadz turun tangan membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan menghidupkan lahan kosong. Tawa dan peluh bercampur menjadi doa ekologis.
Dari kegiatan ini tumbuh nilai-nilai luhur:
kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan cinta pada bumi sebagai rumah bersama.
4. Tafakur Alam: Belajar dari Semut dan Embun
Pelajaran terbesar seringkali datang bukan dari kelas, melainkan dari alam.
Santri diajak duduk di bawah pohon, memperhatikan semut, meresapi embun pagi.
Dari kesunyian itu, mereka mengenal akidah: bahwa alam bukan hadir begitu saja—ia adalah bukti nyata dari kebesaran Allah.
-
Mengapa Ini Penting?
Indonesia memiliki lebih dari 28.000 pesantren—kekuatan kultural dan spiritual yang tak ternilai. Bayangkan jika setiap pesantren memiliki satu kebun organik, satu sistem pengelolaan sampah, dan satu gerakan cinta lingkungan.
Yang lahir bukan hanya generasi santri yang saleh, tapi juga generasi penjaga bumi.
Gerakan kecil ini, bila dilakukan bersama, akan tumbuh menjadi perubahan besar. Ia akan menyebar seperti akar yang merambat diam-diam, lalu menyejukkan seperti embun pagi.
Kalimantan Timur adalah contoh nyata: kaya akan sumber daya, tapi juga rapuh oleh tambang dan industri. Di tengah ancaman itu, pesantren seperti Syekh Chona Kholil menjadi oase—bukan hanya benteng moral, tetapi juga penjaga hutan, air, dan tanah.
Inilah sebabnya tulisan ini penting. Karena krisis lingkung...

 2 hours ago
1
2 hours ago
1
















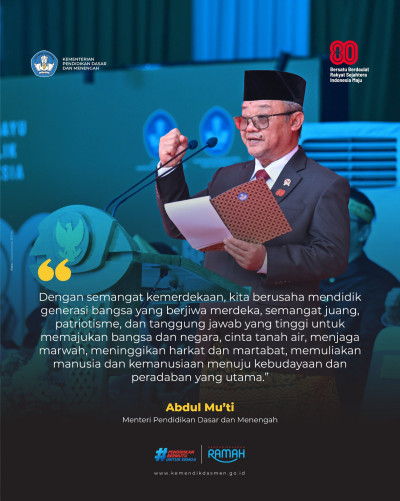


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·