DUA puluh tahun berlalu sejak pemerintah Indonesia dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia. Dengan dimediasi oleh bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan GAM sepakat mengakhiri konflik pada 15 Agustus 2005.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menjadi salah satu tokoh penyambung perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Jusuf Kalla bercerita rintisan upaya perdamaian dimulai pada 2002 saat ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah kabinet Presiden Megawati. Lalu, ia memasukkan upaya rekonsiliasi konflik Aceh menjadi target prioritas di tahun pertama pemerintahan SBY-JK. Alasannya adalah pertimbangan historis dan kepentingan nasional.
“Kalau kita ingin bangun negeri ini, tentu kalau ada konflik jadi ada halangan. (Terlebih) konfliknya antara kita sendiri, antara Indonesia dengan rakyat Indonesia,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 9 Agustus 2025. Dia juga menyebut konflik yang terjadi selama tiga dekade di Aceh mendesak diselesaikan karena menelan korban hampir 20 ribu orang.
Tim negosiator yang diutus JK saat itu terdiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Farid Husain, Direktur Keamanan dan HAM Departemen Luar Negeri Gusti Agung Wesaka Pudja, dan Deputi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Usman Basyah.
Mereka melakukan perundingan rahasia di Helsinki dalam beberapa putaran sejak Januari hingga Agustus 2005. Ketika ditemui di kantornya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sofyan Djalil, menceritakan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan GAM berlangsung sengit karena keinginan Aceh memisahkan diri dari Indonesia demikian besar.
“Pak JK kasih peraturan. Mereka boleh minta apapun kecuali kemerdekaan,” tutur Sofyan Djalil kepada Tempo pada Senin, 11 Agustus 2025.
Sebagai balasannya, pemerintah menuntut agar GAM mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meletakkan senjata mereka. Kedua hal itu termasuk isi dalam nota kesepahaman perjanjian Helsinki yang ditandatangani oleh eks Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, eks pimpinan GAM Malik Mahmud Al Haythar, serta Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Martti Ahtisaari.
Menurut Sofyan, keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah ke GAM didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan cara terhormat. Bukan melalui pengadilan ataupun militeristik kendati GAM merupakan gerakan separatisme.
Dalam sebelas lembar nota kesepahaman itu, pemerintah dan GAM menyepakati perjanjian yang mencakup enam aspek, yaitu; penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; hak asasi manusia; amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat; pengaturan keamanan; pembentukan misi monitoring aceh; serta penyelesaian perselisihan.
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Aceh berhak untuk melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, serta kebebasan beragama.
Pembentukan Partai Politik Lokal hingga Kibarkan Bendera Aceh
Melalui perjanjian itu, Aceh diperbolehkan untuk menggunakan simbol-simbol wilayahnya termasuk bendera, lambang, dan himne. Wilayah perbatasan Aceh tetap mengacu pada perbatasan 1 Juli 1956. Kemudian, Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk untuk mengatur kepemimpinan adat di Aceh.
Hasil perjanjian Helsinki itu lalu menjadi dasar dari pembentukan undang-undang otonomi khusus yang ditindaklanjuti itu melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian dalam hal partisipasi politik, GAM meminta untuk membentuk partai lokal kepada pemerintah Indonesia.
Sofyan Djalil menuturkan, pokok pembahasan pembentukan partai politik lokal adalah substansi yang paling alot dibahas. Menurut Sofyan regulasi Indonesia pada waktu itu tidak mengenal sistem partai politik lokal. “Kalau kami setuju presiden bisa dimakzulkan,” tuturnya. Namun, akhirnya, pemerintah menyetujui permintaan itu dengan syarat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuan atas pembentukan partai politik di Aceh.
Selain itu, perjanjian Helsinki juga menjadi dasar bagi masyarakat Aceh untuk menentukan sendiri calon semua pejabat dalam pemilihan umum di Aceh yang dimulai pada bulan April 2006 hingga seterusnya. Sampai tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh tidak berwenang untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh.
Berikutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi, Aceh memiliki sejumlah keistimewaan lewat perjanjian Helsinki. Seperti berhak berutang kepada luar negeri dan menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan Bank Indonesia. Isu ketimpangan ekonomi menjadi salah satu alasan GAM memberontak karena merasa pemerintah tidak memberikan keadilan bagi daerah yang dijuluki Serambi Mekah itu.
Kesepakatan lainnya ialah Aceh berhak menarik investasi dan wisatawan langsung ke daerahnya, berhak menguasai 70 persen hasil dari semua sumber daya alam di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. “Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pemerintah pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh,” bunyi pasal lainnya.
Amnesti hingga Lahan Pertanian untuk Anggota GAM
Berikutnya, perjanjian Helsinki juga mengatur kesepakatan pemberian amnesti untuk seluruh anggota GAM. Soal amnesti ini diatur dalam pasal 3. Amnesti, kata pasal itu, akan diberikan kepada semua pengikut GAM sesegera mungkin dan paling lambat 15 hari setelah perjanjian diteken.
Semua tahanan politik gerakan itu juga akan bebas tanpa syarat. Tapi, mulai hari itu juga semua penggunaan senjata oleh GAM akan dianggap sebagai pelanggaran. Mereka yang masih memanggul senjata tak akan diberi amnesti.
Pemerintah memberikan amnesti kepada 1.877 aktivis GAM yang menjadi narapidana atau tahanan di berbagai penjara di Indonesia. Pasal amnesti itu juga disatukan dengan urusan penyatuan kembali anggota GAM ke masyarakat, atau yang disebut "reintegrasi". Untuk mendukung reintegrasi itu, pemerintah Aceh akan menyiapkan dana reintegrasi, sedangkan pemerintah Indonesia akan memberikan dana untuk rehabilitasi hak milik warga dan publik yang hancur akibat konflik bersenjata.
Pemerintah juga memberikan lahan pertanian kepada bekas gerilyawan GAM. Pemberian tanah ini juga diberikan dalam rangka kompensasi bagi tahanan politik maupun kepada kalangan sipil yang terdampak.
Sebagaimana disinggung sebelumnya, GAM harus memenuhi permintaan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan senjata. Sofyan Djalil menyebut kesepakatannya bukan dengan menyerahkan senjata kepada Indonesia, melainkan dengan memotong 960 senjata milik GAM. Menurut dia, cara itu tetap memberikan martabat bagi Aceh.
Namun, dalam pasal empat perjanjian Helsinki, disebutkan bahwa GAM sepakat untuk menyerahkan 840 senjata. GAM juga harus berhenti mengerahkan 3 ribu pasukan militernya yang disusul dengan penarikan sejumlah Tentara Nasional Indonesia dan polisi dari wilayah Aceh. Pemerintah berjanji untuk tidak akan mengerahkan tentara secara besar-besaran usai kesepakatan damai ini.
Sementara itu, polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. Adapun tentara bertugas untuk menjaga pertahanan eksternal di Tanah Rencong.
Bila terjadi perselisihan dalam implementasi perjanjian Helsinki, Kepala Misi Monitoring Aceh akan bertugas untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Namun, dalam kasus perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah ataupun keputusan mengikat dari Kepala Misi Monitoring Aceh, maka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama pimpinan politik GAM serta Crisis Management Initiative. Keputusan akhir akan berada di tangan organiasi non-pemerintahan itu yang sedari awal memediasi konflik pemerintah Indonesia dengan GAM.
Menurut mantan Perdana Menteri GAM yang memimpin perundingan di Helsinki, Malik Mahmud Al Haythar, perjanjian Helsinki adalah jalan keluar bagi perdamaian Aceh. Mahmud yang kini menjabat sebagai Wali Nanggroe itu menyebut bahwa kesepakatan antara pemerintah dan GAM adalah wujud dari kompromi.
“Apa yang kami bisa beri kepada (pemerintah) pusat dan apa juga pusat yang bisa beri kepada kami. Itu gift and take lah. Kalau ini sudah bertemu, kan sudah masing-masing ada kepuasan,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

 2 hours ago
1
2 hours ago
1











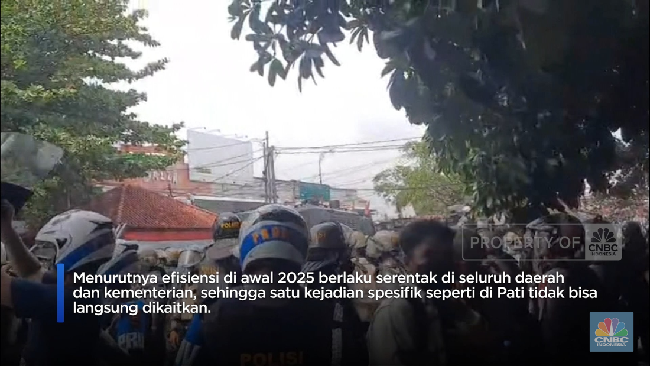








:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·