
Oleh : Achmad Tshofawie; Kordinator Eco-Fitrah, peminat kajian strategis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarah manusia selalu bergulat dengan tanah. Tanah adalah tempat lahir, sumber pangan, ruang tinggal, hingga peristirahatan terakhir. Tak heran jika konflik terbesar umat manusia sering kali berakar pada perebutan tanah. Kini, di abad ke-21, perebutan itu kembali hadir dalam wajah modern: land grabbing.
Korporasi global membeli atau menyewa jutaan hektar lahan pertanian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk kepentingan industri pangan, energi, atau pertambangan. Rakyat lokal kerap terpinggirkan, sementara air, hutan, dan tanah subur berpindah tangan ke perusahaan transnasional.
Dalam konteks inilah, menarik untuk meninjau ulang semboyan "Blut und Boden"-sebuah istilah Jerman yang secara harfiah berarti “Darah dan Tanah”. Di era Nazi, istilah ini dipelintir menjadi dasar ideologi rasis: hanya mereka yang dianggap “ras murni” berhak atas tanah Jerman.
Namun, apakah semboyan ini mutlak harus dibuang ke tong sampah sejarah? Atau justru masih ada sisi reflektif yang bisa dipetik—bukan untuk meniru fasisme, melainkan untuk membangkitkan kembali patriotisme ekologis di Tanah Air kita?
Darah: Identitas,Sejarah, dan Kedaulatan
“Darah” dalam semboyan itu bisa kita pahami bukan sebagai simbol rasial, tetapi sebagai identitas dan sejarah perjuangan bangsa. Darah mengingatkan pada pengorbanan para pahlawan yang merebut tanah air dari kolonialisme.
Darah juga melambangkan ikatan biologis kita dengan bumi-sebagaimana Alquran menegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah (QS. Al-Mu’minun:12). Dengan demikian, “darah” di sini bukan eksklusivitas etnis, melainkan fitrah kemanusiaan: bahwa setiap orang memiliki ikatan hidup dengan tanah tempat ia berpijak.
Dalam konteks Indonesia, “darah” berarti kesadaran bahwa kedaulatan pangan dan energi adalah harga mati. Jika tanah dan air kita dieksploitasi oleh korporasi asing, sesungguhnya kita sedang “ditransfusi” oleh darah orang lain-kehilangan denyut kehidupan sendiri. Patriotisme sejati berarti berani menjaga denyut nadi bangsa ini tetap mengalir dari sumber-sumber aslinya.
Tanah: Ibu Kehidupan dan Ekologi Fitrah
“Tanah” adalah ibu kehidupan.Ia menumbuhkan beragam jenis tanaman padi, jagung, kedelai, kopi, rempah,dll-semua yang menjadi identitas kuliner sekaligus ekonomi bangsa. Tanah juga menyimpan air, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menyuburkan hutan.
Dalam tradisi Nusantara, tanah selalu disakralkan: ada istilah tanah tumpah darah, tanah pusaka, hingga ungkapan sawah ladang adalah ibu kehidupan. Alquran juga menyebut tanah yang baik (al-ardh at-thayyibah) akan menumbuhkan tanaman yang subur dengan izin Allah (QS. Al-A‘raf:58). Inilah yang disebut mizan-keseimbangan kosmik yang harus dijaga.
Namun, kapitalisme global melihat tanah sekadar sebagai komoditas. Sawah berubah menjadi kawasan industri, hutan menjadi perkebunan monokultur, dan gunung dikeruk untuk tambang. Padahal, tanah adalah ruang hidup, bukan sekadar aset. Di sinilah patriotisme tanah air harus muncul: tanah bukan untuk dijual, tetapi untuk dikelola dengan cinta dan tanggung jawab.
Membaca Ulang Blut und Boden: Dari Fasisme ke Eco-Patriotisme
Memang, kita tidak bisa menafikan sejarah kelam semboyan Blut und Boden. Namun, jika didekonstruksi, kita menemukan pesan tersirat yang masih relevan: manusia tidak bisa
dipisahkan dari tanah. Di Indonesia, pembacaan ulang semboyan ini justru bisa menjadi mantra kebangkitan eco-fitrah.
Alih-alih rasisme, mari jadikan ia sebagai, pertama-tama sebagai seruan ekologis. Darah adalah kehidupan, tanah adalah sumbernya. Maka siapa pun yang hidup di bumi Indonesia wajib menjaga keseimbangan alam.
Selanjutnya sebagai seruan kedaulatan pangan. Tanah kita jangan dikuasai oleh asing; sawah dan ladang harus memberi makan anak bangsa sendiri terlebih dahulu.
Kemudian seruan spiritual. Tanah adalah amanah dari Allah, bukan sekadar aset ekonomi.
Mengkhianati tanah berarti mengkhianati fitrah penciptaan.
Dengan demikian, Blut und Boden tidak lagi menjadi jargon fasis, tetapi ditransformasi menjadi “Fitrah dan Tanah Air”-sebuah etos yang relevan dengan perjuangan melawan land grabbing dan dominasi korporasi asing.
Patriotisme Tanah Air: Dari Retorika ke Aksi
Patriotisme tanah air bukan sekadar menyanyikan lagu kebangsaan di upacara. Ia harus diwujudkan dalam aksi nyata. Pertama sebagai reforma agraria sejati. Yakni, memberikan akses tanah kepada petani kecil, bukan kepada korporasi.
Kemudian agrofitrah. Yakni menghidupkan kembali sistem pertanian organik, agroekologi, dan kearifan lokal yang menyatu dengan tanah.
Ketiga, kedaulatan air dan energi. Air, sungai, dan sumber energi harus dikelola negara untuk rakyat, bukan dijual kepada swasta asing.
Kempat, sebagai pendidikan ekologis. Generasi penerus harus diajarkan bahwa mencintai tanah air bukan hanya soal sejarah perang, tapi juga menjaga ekosistem sungai,danau, laut,hutan, dan sawah.
Terakhir, gerakan konsumen patriotik. Yakni, memilih produk pangan lokal, menolak dominasi impor, dan menghidupkan kembali pasar rakyat.
Dari Darah ke Tanah, Dari Fitrah ke Patriotisme
Spirit Blut und Boden memang pernah disalahgunakan untuk menindas. Tetapi di tangan bangsa yang merdeka, semboyan ini bisa dibaca ulang sebagai panggilan patriotisme ekologis. Darah berarti kehidupan yang diwariskan para pejuang. Tanah berarti ruang hidup yang harus dijaga. Fitrah berarti keseimbangan yang dititipkan Allah kepada manusia.
Maka, di tengah gempuran land grabbing, eksploitasi tambang, dan krisis ekologi global, mari kita kembalikan patriotisme tanah air bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam praktik menjaga tanah, air, dan hutan Indonesia untuk generasi mendatang.
Karena sejatinya, bangsa tanpa tanah adalah bangsa tanpa darah.

 1 hour ago
2
1 hour ago
2







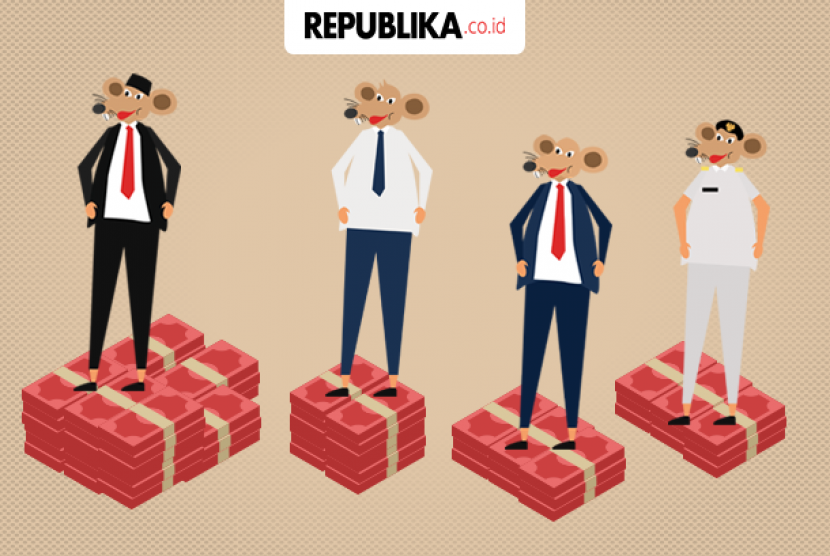




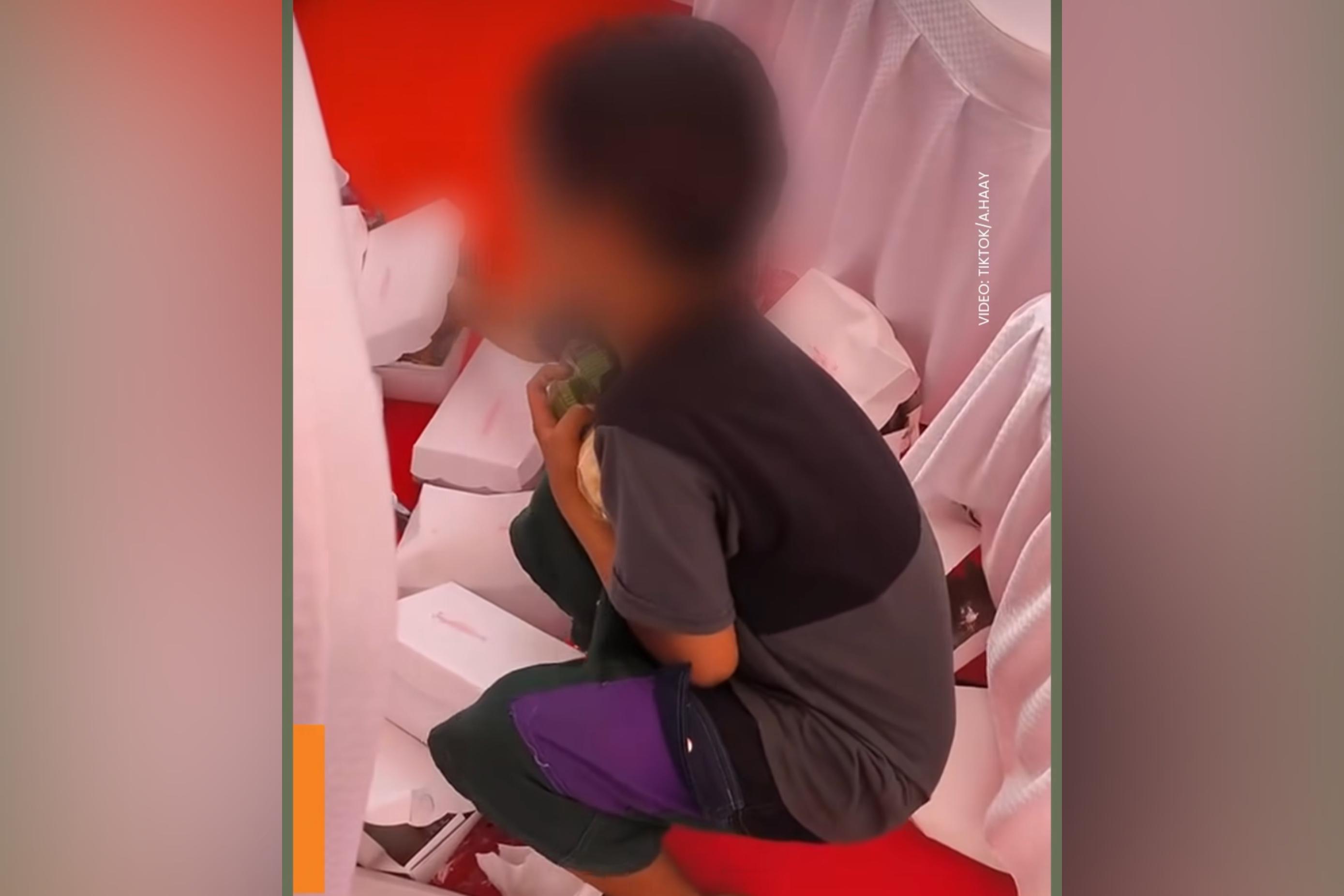




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·