Interaksi selama berabad-abad antara Indonesia dan Belanda sudah tentu menyediakan ruang tersendiri untuk saling memberi warna pengaruh. Ambil misal saja sejumlah kuliner Indonesia, seperti nasi goreng, satai, dan gado-gado hingga kini masih akrab dengan cecap lidah masyarakat di Negeri Belanda. Gamelan dan tari-tarian Nusantara, pun mereka kenal dan ada sebagian di antaranya yang tertarik untuk mempelajarinya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kata “gamelan” sudah masuk dalam khazanah kosakata bahasa Belanda. Kita tidak perlu heran, jika suatu kali mendengar ada orang dari Negeri Kincir Angin itu berkata kepada temannya, “Ik hou van de melodieuze geluid van gamelan” (Saya menyukai bunyi gamelan yang terdengar merdu). Di sini tampak, betapa kata “gamelan” telah padu menyatu dengan kata-kata lain dari bahasa Belanda.
Demikian halnya dengan kata “keris” juga telah mendapatkan tempat dalam bahasa Belanda. Kalimat “Het verhaal van de keris die Empu Gandring maakte, is ronduit angstaanjagend” (Kisah keris buatan Empu Gandring itu sungguh mengerikan), tetap memiliki standar gramatikal yang terjaga.
Dan, sebutan untuk nama kuliner asal Indonesia pun agaknya tetap mereka pertahankan. Seperti tertuang dalam lagu keroncong “Geef Mij Maar Nasi Goreng” (Beri Aku Nasi Goreng) ciptaan Wieteke van Dort (1977).
Demikian pula sebaliknya dengan bahasa Indonesia. Ada ratusan kata yang terentang dari abjad A hingga Z yang ternyata merupakan serapan dari bahasa Belanda. Tidak semua asli Belanda memang. Ada yang sebelumnya diserap bahasa itu dari bahasa lain, seperti Spanyol atau Prancis.
Kebanyakan kata-kata serapan dari bahasa Belanda itu mengalami adaptasi atau akomodasi fonetis. Proses ini terjadi ketika kata dari bahasa serapan mengalami penyesuaian ejaan dan/atau lafal sesuai dengan sistem fonologi bahasa penerima.
Dari “Arsitek” hingga “Aula”
Misalnya kata “arsitek”. Ia merupakan hasil adaptasi fonetis dari “architect”. Di sini terjadi penyesuaian fonem /ch/ menjadi /s/ dan fonem /ct/ menjadi /k/. Selanjutnya kata “arsip” yang diserap dari “archief”. Terjadi penyesuaian fonem /cf/ dengan /s/ dan /ie/ dengan /i/ serta perubahan bunyi /f/ dengan /p/.
Kemudian kata “aspal” yang merupakan hasil serapan dari “asfalt”. Pada kasus akomodasi fonetis ini, terjadi perubahan fonem /f/ dengan /p/ dan penghilangan fonem /t/. Lalu kata “asuransi (assurantie)”, ada penyederhanaan fonem dari /ss/ menjadi hanya satu /s/ saja; perubahan fonem /t/ menjadi /s/; serta penyesuaian fonem /ie/ menjadi /i/.
Selain itu ada sejumlah kata yang mengalami proses adopsi. Bahasa penerima (Indonesia) melakukan penyerapan secara persis sesuai dengan versi penulisan bahasa asalnya (Belanda).
Contohnya “aula” (De aula van de school is mooi ingericht [Aula sekolah itu tertata dengan indah]); “asbak” (Waar is de asbak? [Di mana asbak itu?]); “alias” (De verdachte, alias de man met de hoed, werd voor de rechter gebracht [Tersangka, alias orang yang mengenakan topi, dibawa ke pengadilan]).

 18 hours ago
1
18 hours ago
1











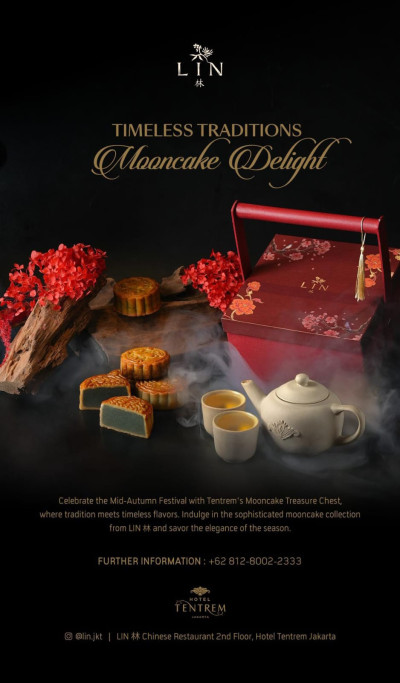




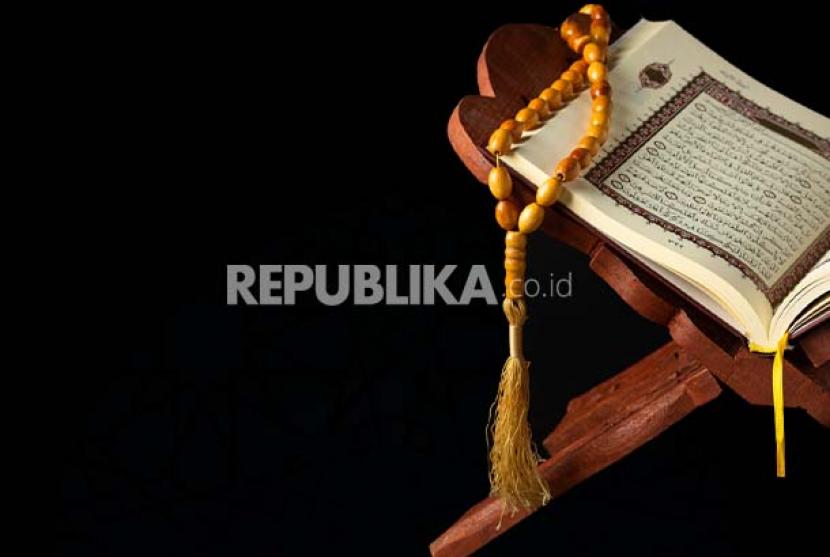



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4104946/original/042371200_1659067441-nathana-reboucas-c4aT8MfEzdw-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5300627/original/017310100_1753895433-Screenshot_2025-07-30_234419.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·