 Ilustrasi aktivitas logistik ekspor impor (Andy Li/Unsplash)
Ilustrasi aktivitas logistik ekspor impor (Andy Li/Unsplash) Sudah bukan rahasia lagi bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah lama mengalami kebocoran. Kebocoran demi kebocoran ini, dari jutaan data pemilih hingga informasi kependudukan, tidak pernah benar-benar mendapatkan respons struktural yang tegas dari negara.
Pada konteks ekonomi, produk-produk Amerika Serikat juga telah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Minuman bersoda merek global, jaringan restoran cepat saji yang menjadi ikon budaya populer, hingga makanan seperti sandwich dan roti sosis, semuanya menunjukkan betapa dominannya budaya konsumsi Barat. Bahkan dalam sektor teknologi, layanan digital dan telekomunikasi dari Silicon Valley telah membentuk pola perilaku dan preferensi warga lokal. Ini bukan sekadar invasi ekonomi, tapi ekspansi budaya yang halus dan berkelanjutan.
Namun, yang kini patut diwaspadai bukan sekadar dominasi produk-produk konsumsi atau penetrasi budaya asing. Tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap produk dari luar Amerika Serikat, termasuk dari Indonesia, membawa implikasi lebih dalam dari sekadar perdagangan. Sebab di balik retorika proteksionisme tersebut, tersembunyi tekanan terhadap negara-negara berkembang agar tunduk pada struktur pasar global yang timpang.
Salah satu isu paling krusial dari kebijakan dagang ini adalah potensi keterpaksaan bagi Indonesia untuk membuka keran ekspor sumber daya mineral secara langsung tanpa melalui proses hilirisasi. Padahal, sejak masa Presiden Joko Widodo, Indonesia telah berkomitmen pada kebijakan hilirisasi untuk memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tapi juga diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi juga membuka lapangan kerja, memacu transfer teknologi, dan memperkuat basis industri nasional.
Salah satu isu paling krusial dari kebijakan dagang ini adalah potensi keterpaksaan bagi Indonesia untuk membuka keran ekspor sumber daya mineral secara langsung tanpa melalui proses hilirisasi.Kebijakan tarif 19% yang membebani produk olahan justru mendorong negara-negara seperti Indonesia untuk memilih jalan pintas, yaitu mengekspor bahan mentah agar tetap kompetitif di pasar global. Jika ini terjadi, maka kebijakan hilirisasi terancam gagal. Lebih dari itu, negara-negara mitra yang selama ini telah membangun pabrik ekstraksi dan pemurnian di Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, bisa merasa dirugikan karena Indonesia tiba-tiba berubah arah demi menyesuaikan diri dengan tekanan pasar Amerika. Pun, barang-barang AS di pasar Indonesia juga akan banyak diprediksi tak berubah harganya karena banyak yang dibuat di Tiongkok, bukan AS.
Menurut data Kementerian ESDM, sejak diterapkannya larangan ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2020, nilai ekspor nikel olahan Indonesia melonjak dari USD 6 miliar menjadi lebih dari USD 20 miliar pada 2023.
Sebagai perbandingan, Korea Selatan mengambil langkah cerdas dengan mengintensifkan kerja sama bilateral di luar bayang-bayang dominasi AS. Negeri Ginseng itu memperluas pasar ekspornya ke Asia Tengah dan Timur Tengah, serta memperkuat sektor teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Alih-alih menyerah pada tarif tinggi, Korea Selatan mengalihkan strategi industri ke sektor-sektor yang lebih resilien dan bernilai tinggi.
Pada laporan WTO 2024, Korea Selatan berhasil mempertahankan pertumbuhan ekspornya sebesar 5,3% meskipun diterpa tarif tinggi dari AS. Hal yang juga penting dicatat adalah bagaimana kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi memainkan peran krusial dalam menyikapi dinamika tarif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam membangun aliansi perdagangan regional, memperkuat posisi di ASEAN, dan memanfaatkan perjanjian dagang seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) untuk mengimbangi tekanan dari negara adidaya. Jika tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam kontestasi dagang global.
Sudah waktunya Indonesia melihat bahwa proteksionisme bukan sekadar hambatan, tapi juga peluang untuk merevisi ulang orientasi pembangunan nasional. Jika tarif 19% dianggap sebagai pemicu krisis, maka krisis ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat industri dalam negeri, memperluas diplomasi perdagangan, dan membenahi regulasi agar investor asing tidak hanya melihat Indonesia sebagai tambang mentah, tetapi sebagai mitra strategis dalam rantai pasok global.
Bukan berarti semua bentuk kerja sama dengan AS harus ditolak. Namun, Indonesia harus cerdas dalam membedakan mana yang menguntungkan secara struktural dan mana yang hanya mengulang pola ketergantungan lama. Dalam dunia multipolar seperti sekarang, kerja sama harus berbasis pada kepentingan nasional, bukan pada tekanan hegemonik.
Oleh karena itu, tarif 19% bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah cermin yang memperlihatkan posisi kita yang masih lemah dalam rantai nilai global. Tapi justru dari kelemahan ini, Indonesia bisa belajar untuk tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah dunia, tetapi menjadi pemain utama dalam ekonomi bernilai tambah tinggi. Seperti Korea Selatan, kita pun bisa menulis ulang kisah ekonomi kita sendiri.

 3 weeks ago
2
3 weeks ago
2














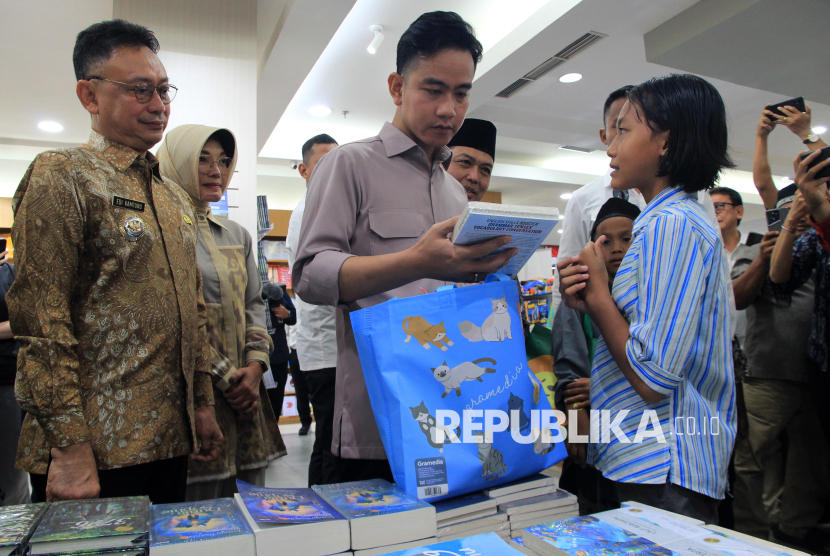





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·