Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong transformasi digital birokrasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Arsitektur SPBE Nasional menunjukkan semangatnya secara jelas, yaitu menjadikan birokrasi lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi cukup untuk mengubah cara kerja birokrasi?
Di atas kertas, SPBE menjanjikan banyak hal, misalnya interoperabilitas data, pelayanan satu pintu, sistem pengukuran kinerja elektronik, hingga integrasi lintas sektor. Namun dalam praktiknya, banyak inovasi SPBE justru terserap ke dalam pola kerja birokrasi lama. Aplikasi dibuat tanpa integrasi, e-kinerja diukur berdasarkan presensi, dan dashboard digital tetap bergantung pada input manual.
Masalah utamanya bukan pada teknologinya, tetapi pada struktur birokrasi yang terlalu tangguh untuk diubah. Struktur ini merupakan enduring structure--pola relasi kekuasaan, norma kerja, dan logika prosedural yang sudah lama terbentuk dan tetap bekerja meskipun ada kebijakan baru.
Contohnya jelas dalam sistem insentif. Tunjangan kinerja yang dimaksudkan untuk mendorong meritokrasi, pada kenyataannya hanya bergeser menjadi tambahan penghasilan berbasis absensi. Reformasi berbasis data pun seringkali hanya mengganti formulir fisik menjadi digital, tanpa mengubah logika kerja hierarkis dan sektoral.
SPBE bukan sekadar soal aplikasi. Ia membutuhkan perubahan dalam cara berpikir birokrasi, dari budaya dokumentatif ke budaya kolaboratif; dari logika asal selamat ke logika akuntabilitas berbasis hasil. Sayangnya, warisan birokrasi Weberian yang menekankan stabilitas, kepatuhan, dan kontrol vertikal masih sangat kuat. Bahkan ketika sistem digital diperkenalkan, yang berubah hanya tampilannya—bukan cara bekerjanya.
Maka tak heran jika SPBE kerap berakhir sebagai etalase reformasi. Ia tampak maju di permukaan, namun tidak cukup mengguncang struktur dalam. Kita sedang berhadapan dengan transformasi yang bersifat teknologis, tapi bukan transformatif.
Pertanyaannya kini, beranikah kita mengubah bukan hanya perangkat lunaknya, tetapi juga cara kita memandang dan mempraktikkan birokrasi?

 2 hours ago
1
2 hours ago
1






















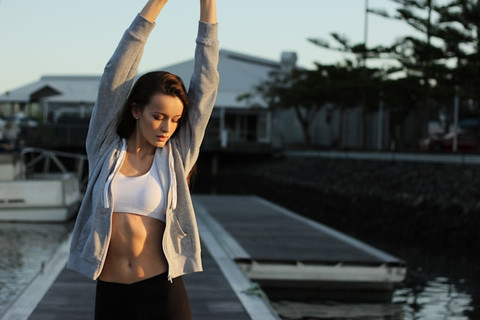





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)









 English (US) ·
English (US) ·