 Pembukaan konferensi, sumber: Dok. Pribadi.
Pembukaan konferensi, sumber: Dok. Pribadi.Tanggal 29 Juli 2025 menjadi momentum berharga, ketika diundang menghadiri pembukaan konferensi internasional tentang persaudaraan kemanusiaan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta.
Acara ini dibuka secara resmi oleh tiga tokoh penting: Prof. Jamhari selaku Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Dr. Khalid Al-Ghaith sebagai Sekretaris Jenderal Higher Committee of Human Fraternity (HCHF), dan Prof. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ketiganya, dengan karisma dan tanggung jawab moral mereka, menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya membangun dunia yang lebih damai di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Diselenggarakan atas kerja sama antara UIII dan HCHF, konferensi ini menjadi simbol nyata dari kolaborasi lintas bangsa dan lintas iman yang tak hanya penting secara simbolik, tetapi juga mendesak secara praktis bagi masa depan peradaban dunia.
Tema besar konferensi, “Maju dalam Persaudaraan Kemanusiaan di Tengah Ketidakpastian Global: Menuju Peradaban Dunia yang Lebih Damai dan Sejahtera,” (Advancing Human Fraternity Amidst Global Uncertainties: Toward a More Peaceful and Prosperous World Civilization) bukan sekadar slogan, melainkan refleksi mendalam terhadap kenyataan pahit yang sedang kita alami.
Perang dan kekerasan meningkat di berbagai belahan dunia, krisis kemanusiaan memburuk, dan polarisasi ideologi serta identitas terus memperdalam jurang di antara komunitas global.
Dalam konteks inilah, konferensi tersebut menjadi ruang dialog yang tidak hanya mengajak kita merenung, tetapi juga mendorong kita bertindak. Persaudaraan kemanusiaan bukan lagi wacana ideal, melainkan kebutuhan konkret demi kelangsungan hidup bersama.
Yang paling membekas bagi saya selama konferensi tersebut adalah penekanan konsisten dan tulus terhadap pentingnya membangun kolaborasi antarumat manusia.
Tidak sekadar retorika, gagasan ini menjadi komitmen kolektif yang terasa hadir dalam setiap sesi, baik formal maupun informal.
Pembicara dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan keahlian—dari akademisi, pemuka agama, hingga aktivis—bersepakat bahwa kolaborasi lintas batas adalah kunci untuk menghadapi disintegrasi sosial yang semakin merajalela.
Kita semua diundang, bahkan didesak, untuk mengubah cara berpikir: dari eksklusivitas menuju inklusivitas; dari kecurigaan menuju kepercayaan; dari konflik menuju harmoni.
Dalam perenungan saya, pesan konferensi ini terasa sejalan dan bahkan sejiwa dengan Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Kemanusiaan untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan (The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together), yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmed el-Tayeb pada Februari 2019.
Dokumen tersebut telah menjadi tonggak sejarah yang membuktikan bahwa dialog antaragama bisa menjangkau tingkat lebih tinggi: bukan hanya toleransi, tetapi persaudaraan sejati.
Ia menyerukan agar semua manusia, tanpa kecuali, dihormati martabatnya dan dilibatkan dalam proses penciptaan perdamaian global yang adil dan berkelanjutan. Bagi saya, konferensi di Jakarta adalah lanjutan konkret dari dokumen bersejarah tersebut.
Dokumen Abu Dhabi bukanlah pernyataan simbolik semata. Ia merupakan peta jalan moral dan spiritual yang mengundang kita meninggalkan narasi-narasi lama berbasis konflik dan kecurigaan. Ia mengajak umat manusia menyadari bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan rahmat.
Perbedaan bisa menjadi sumber daya bersama untuk membangun dunia yang lebih kuat dan penuh kasih. Dengan demikian, dialog bukan lagi sekadar komunikasi, tetapi juga transformasi bersama.
 Ilustrasi bersatu dalam keberagaman. Foto: Shutterstock
Ilustrasi bersatu dalam keberagaman. Foto: ShutterstockDalam dunia yang terus berubah dan kadang terasa penuh kekacauan, pesan dalam dokumen ini hadir seperti kompas yang menuntun arah etis dan spiritual kita.
Nilai-nilai utama yang ditegaskan dalam dokumen tersebut—kasih sayang, toleransi, dan saling pengertian—merupakan fondasi bersama dari berbagai tradisi agama dan filsafat.
Dokumen ini tidak menawarkan jalan pintas, tetapi mengingatkan kita bahwa hanya melalui perjuangan bersama dan komitmen terus-menerus kita dapat mewujudkan kedamaian sejati.
Ketika dunia dilanda konflik di Gaza, Ukraina, dan banyak tempat lain, nilai-nilai ini tidak bisa ditunda pelaksanaannya.
Dalam setiap tindakan nyata—baik melalui pendidikan, dialog antaragama, ataupun proyek-proyek sosial—nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dan dirawat.
Konferensi yang saya hadiri kemarin merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. Bukan hanya melalui pidato dan diskusi, tetapi juga dalam perjumpaan yang penuh ketulusan antarpeserta. Saya menyaksikan bagaimana perbedaan menjadi kekayaan, bukan beban.
Orang-orang dari agama, bangsa, dan pandangan yang beragam duduk bersama, mendengar dengan hormat, dan merumuskan solusi bersama. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga: bahwa damai tidak dibangun oleh keseragaman, tetapi oleh kerelaan untuk saling memahami dan berjalan bersama dalam perbedaan.
Peristiwa semacam ini membuktikan bahwa dunia belum kehilangan harapan. Ketika lembaga pendidikan seperti UIII dan lembaga internasional seperti HCHF memfasilitasi pertemuan lintas budaya dan agama, kita sedang menyaksikan benih-benih harapan yang sedang ditanam bagi generasi mendatang.
Kolaborasi lintas sektor yang lahir dari konferensi ini dapat menjadi model yang menginspirasi bagi negara-negara lain. Dunia tidak kekurangan deklarasi dan janji; yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberanian untuk menerjemahkan nilai-nilai luhur ke dalam aksi kolektif yang berkelanjutan.
Kita sebagai bagian dari masyarakat global, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk tidak bersikap pasif. Justru di tengah ketidakpastian global inilah, partisipasi aktif kita menjadi semakin bermakna.
Membangun jembatan kemanusiaan tidak selalu berarti menciptakan program berskala besar; sering kali ia dimulai dari hal kecil: mendengarkan dengan empati, membuka ruang dialog, dan mengakui kemanusiaan orang lain.
Setiap langkah menuju pengakuan martabat manusia adalah batu bata yang membentuk jembatan besar kemanusiaan. Dan semua itu harus dimulai dari kesadaran pribadi kita masing-masing.
Sebagai refleksi akhir, kita harus bertanya kepada diri sendiri: apakah kita bersedia merobohkan tembok-tembok kecurigaan, prasangka, dan kebencian yang mungkin telah lama kita bangun? Apakah kita mampu mengubah pandangan kita tentang “yang lain” bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sahabat dalam perjuangan bersama mewujudkan dunia yang lebih damai?
Dokumen Abu Dhabi dan konferensi internasional kemarin memberi jawaban jelas: ya, itu semua mungkin—asal kita punya niat, keberanian, dan tekad untuk memulai dari diri sendiri dan komunitas terdekat.
Akhirnya, membangun ikatan kemanusiaan merupakan proses panjang yang menuntut dedikasi dan ketekunan, bukan hanya satu kali konferensi atau satu dokumen deklaratif. Tetapi dari titik ini, kita sudah memiliki fondasi kuat: prinsip-prinsip universal yang diakui lintas agama dan bangsa. Kita memiliki model konkret yang bisa direplikasi dan dikembangkan.
Sekarang, tinggal giliran kita untuk memastikan bahwa semua nilai luhur itu tidak berhenti sebagai wacana elitis, tetapi hidup dalam tindakan nyata, sehari-hari.
Karena hanya dengan begitu, kita bisa mengatakan kesungguhan dalam melangkah maju membangun peradaban dunia lebih damai dan sejahtera.

 3 weeks ago
2
3 weeks ago
2










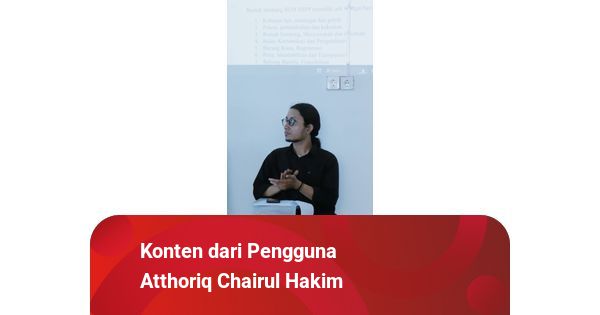








:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·