 Rezal Kusumaatmadja, dalam Forum Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) seri ke-11 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/7) lalu. Foto: Dok. PRAKSIS
Rezal Kusumaatmadja, dalam Forum Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) seri ke-11 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/7) lalu. Foto: Dok. PRAKSISKerusakan alam yang kian masif di berbagai belahan dunia bukan lagi bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Bagi Rezal Kusumaatmadja, hal itu sudah menjadi persoalan sosial, politik, bahkan spiritual. Pandangan itu ia sampaikan dalam Forum Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) seri ke-11 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/7) lalu, dalam diskusi bertajuk “Solusi Tanding Demi Memperkuat Ketahanan Ekosistem Berbasis Komposisi Modal Organik.”
Mengacu pada ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus yang terbit pada 2015, Rezal menegaskan pentingnya pendekatan lintas dimensi dalam merawat bumi. Setiap upaya untuk melestarikan lingkungan harus dilakukan sebagai bagian dari kesadaran bahwa bumi adalah “rumah bersama” yang perlu dirawat secara kolektif oleh seluruh makhluk yang menghuninya.
“Inisiatif sekecil apa pun untuk melestarikan alam akan jadi sumbangan penting dalam mengangkat keseluruhan sistem menuju ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Rezal. Di tengah kondisi alam yang secara sistemik sudah kacau dan tak seimbang, menurutnya, pelibatan aspek spiritual, moral, dan etis menjadi sangat penting.
Ia menilai, penyelesaian teknis semata terhadap kerusakan lingkungan justru tidak memadai. Manusia, kata Rezal, bukan satu-satunya penghuni planet ini. Bahkan jauh sebelum manusia hadir, alam sudah ada—hidup, tumbuh, dan memiliki sistemnya sendiri. Ketika dimensi spiritual dan moral hilang dari cara pandang manusia terhadap alam, muncullah ilusi bahwa alam semata diciptakan untuk dikuasai dan dieksploitasi sehabis-habisnya.
“Konsep alam sebagai creation (ciptaan) membuat manusia cenderung eksploitatif. Akan beda hasilnya jika manusia memandang alam sebagai celebration, yakni sebagai sebuah sistem besar di mana setiap bagiannya saling menghidupi dan memuliakan,” jelasnya.
Kesadaran itu pula yang mendorong Rezal memulai sebuah proyek pelestarian alam yang ia beri nama Project Tampelas. Proyek ini berlokasi di Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bersama sejumlah pihak, proyek ini dijalankan melalui PT Rimba Makmur Utama (RMU), di mana Rezal merupakan salah satu pendiri sekaligus komisaris utama.
Di sana, mereka mengelola dan merestorasi hutan rawa gambut seluas 157.875 hektar. Proyek ini dirancang dengan pendekatan ekonomi restoratif—menggabungkan pelestarian alam dengan pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan air gambut untuk membudidayakan ikan gabus.
 Rezal Kusumaatmadja, dalam Forum Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) seri ke-11 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/7) lalu. Foto: Dok. PRAKSIS
Rezal Kusumaatmadja, dalam Forum Praksis (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) seri ke-11 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/7) lalu. Foto: Dok. PRAKSISLangkah itu memberi dampak ganda. Pertama, warga yang sebelumnya mengandalkan perambahan hutan untuk bertahan hidup, kini beralih ke kegiatan yang melestarikan lingkungan. Kedua, ikan gabus yang dibudidayakan ini bisa diolah menjadi albumin, sebuah produk bernilai ekonomi tinggi yang memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat.
“Melalui kerja sama dengan masyarakat, lahan gambut yang rusak bisa dipulihkan. Masyarakat tidak hanya berhenti merusak hutan, tetapi juga terlibat aktif merawatnya,” ungkap Rezal, lulusan Cornell University dan University of Hawaii, Amerika Serikat.
Skema ekonomi restoratif ini juga dikaitkan dengan inisiatif perdagangan karbon (carbon trading). Uang yang dihasilkan dari skema tersebut kemudian digunakan kembali untuk memperluas proyek-proyek pelestarian lingkungan. Pendekatan ini, menurut Rezal, justru jauh lebih efektif dibanding program konservasi konvensional yang kerap terhambat oleh tumpukan regulasi dan birokrasi.
Ia menyebut Project Tampelas sebagai bentuk solusi tanding—gagasan tandingan yang tidak melulu bergantung pada skema formal pemerintahan, melainkan tumbuh dari inisiatif warga, kerja kolektif, dan visi yang menyatu dengan alam dan komunitas.
Dalam praktiknya, solusi tanding ini juga menjadi respons atas kenyataan bahwa dalam banyak kasus, regulasi yang terlalu pekat justru merusak “tenunan sosial” yang sudah terbentuk secara alami di masyarakat. “Apa yang kami lakukan di Tampelas ini adalah upaya untuk memantik imajinasi publik tentang bentuk lain dalam merawat bumi,” kata Rezal.
Baginya, Project Tampelas bukan sekadar proyek konservasi, melainkan laboratorium hidup yang menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring. Semua itu dimulai dengan satu prinsip dasar: bahwa manusia bukan penguasa tunggal atas bumi, melainkan bagian dari ekosistem besar yang harus dirawat bersama.

 1 month ago
2
1 month ago
2












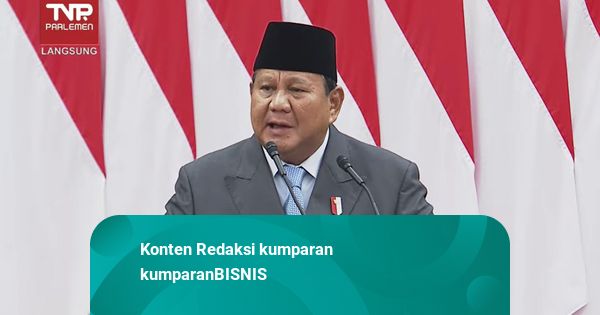






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·