 Suyoto, Chancellor United In Diversity, Pengajar Unmuh Gresik(Dok Ist)
Suyoto, Chancellor United In Diversity, Pengajar Unmuh Gresik(Dok Ist)
BANGSA tumbuh berkembang bila mampu beradaptasi dan berinovasi. Sejarah membuktikan, peradaban yang tidak sigap menjawab perubahan justru tertinggal. Pendidikan tinggi hadir untuk menggerakkan proses adaptasi itu—menghasilkan manusia unggul, ilmu pengetahuan baru, serta inovasi yang relevan.
Edward Clewley (2020) menulis, pertumbuhan perguruan tinggi senantiasa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi MIT terhadap perekonomian Amerika bahkan diperkirakan mencapai 10 persen GDP, terutama melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan alumninya.
Di Indonesia, idealisme itu berwujud dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, praktiknya sering terjebak rutinitas akademik dan administrasi. Sinergi multipihak—mahasiswa, dosen, industri, pemerintah, masyarakat—belum terbangun optimal. Padahal, hanya dengan ekosistem kolaboratif itulah pendidikan tinggi dapat benar-benar memberi dampak sosial berkelanjutan.
Banyak, tapi Apakah Relevan?
Saat ini kita memiliki 26.886 program studi (prodi) di PTN dan PTS. Bidangnya beragam: pendidikan 5.700, teknik 4.800, sosial 4.100, kesehatan 3.300, ekonomi 3.300, pertanian 1.800, agama 1.700, MIPA 1.000, humaniora 719, dan seni 385 (data Dirjen Dikti 2021).
Jumlahnya besar, tetapi pertanyaan kuncinya: apakah semuanya relevan menjawab tantangan bangsa? Banyak prodi lahir sekadar mengikuti tren. Tahun 1980–90-an booming pertanian dan pendidikan; belakangan informatika dan ekonomi. Bahkan, prodi baru kerap muncul bukan karena kebutuhan masa depan, tetapi karena kampus harus menarik mahasiswa agar tetap hidup.
Masalah lain adalah regulasi. Persyaratan dosen linier S1–S2 menyulitkan lahirnya prodi yang benar-benar dibutuhkan, misalnya logistik atau supply chain. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan bahwa pendidikan tinggi harus adaptif dan antisipatif, bukan sekadar mengulang nama prodi yang ada.
Belajar dari Desain Prodi Baru
Saya terlibat dalam desain prodi Happy Digital X: Cities, Systems, Product, and Service, sebuah inisiatif United In Diversity bersama Prof Edward Crawley (MIT) dan Tsinghua University. Prodi ini dirancang untuk menjawab tantangan transformasi digital perkotaan agar berkelanjutan.
Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa desain prodi harus berbasis kebutuhan nyata. Mulai dari identifikasi tantangan, mendengar stakeholder, benchmarking global, melibatkan pakar, hingga evaluasi berkelanjutan. Proses ini bersifat siklus—seperti pesan almarhum A. Malik Fadjar: “start from beginning and the end to beginning.”
Dengan cara itu, prodi menjadi wadah sinergi, bukan sekadar tempat kuliah. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi masuk ke dalam persoalan nyata dan menciptakan solusi yang bermanfaat.
Agenda Transformasi Nasional
Apa yang saya alami sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto. Beliau menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Lewat program “Diktisaintek Berdampak”, Prof Brian mendorong agar perguruan tinggi: 1. Berkeadilan – membuka akses dan kualitas merata di seluruh negeri. 2. Relevan – riset dan prodi menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar tren.3. Berdampak sosial – hasil inovasi harus menyentuh masyarakat, bukan berhenti di jurnal.
Beliau juga memperkenalkan konsep Universitas 4.0 : kampus yang inklusif, inovatif, berkelanjutan, dan berkolaborasi dalam quadruple helix (akademisi–industri–pemerintah–masyarakat). Selain itu, ia menekankan pentingnya world-class universities yang tetap berpihak pada agenda nasional, seperti pangan, energi, kesehatan, dan hilirisasi.
Inspirasi Global
Kita bisa belajar dari dunia. MIT menjadi teladan universitas entrepreneurial lewat model Triple Helix (akademisi–industri–pemerintah). Di Cile, strategi Clover 2030 Engineering mereformasi pendidikan teknik dengan kurikulum singkat, riset relevan, multidisiplin, dan berorientasi tanggung jawab sosial.
Konsorsium internasional seperti ECIU (Eropa) atau AUA (Asia) membuktikan bahwa jaringan antaruniversitas mampu memperkuat mobilitas mahasiswa, riset kolaboratif, dan inovasi regional.
Menuju Indonesia Emas
Jika ingin mewujudkan Indonesia Emas, pendidikan tinggi kita harus berani keluar dari jebakan formalitas dan tren sesaat. Prodi harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata bangsa, dijalankan dengan siklus evaluasi berkelanjutan, dan didukung kebijakan yang berpihak pada dampak sosial.
Dengan sinergi akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat, pendidikan tinggi bisa menjadi fondasi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing global. Inilah saatnya memastikan program studi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menciptakan solusi nyata untuk masa depan Indonesia.
Dalam rangka terciptanya gairah dan memudahkan peta jalan Pendidikan Tinggi Indonesia bertransformasi, United In Diversity menyediakan forum gotong royong saling memperkuat dengan mengadopsi framework CDIO yang diperluas. Proses gotong royong dimulai dari self assessment dan penyusunan peta jalan transformasi.
Lalu berdasarkan keadaanya masing masing dapat terlibat sekaligus sebagai pembelajar, partner dan eccelerator. Sehingga kekuatan satu lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi potensi positif bagi lainnya. Tidak ada kemajuan tanpa suasana proses inclusive collaboration atau gotong royong terbuka. (H-2)

 2 hours ago
1
2 hours ago
1





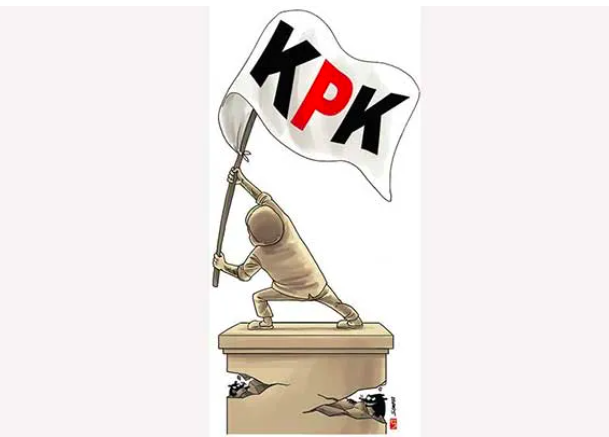







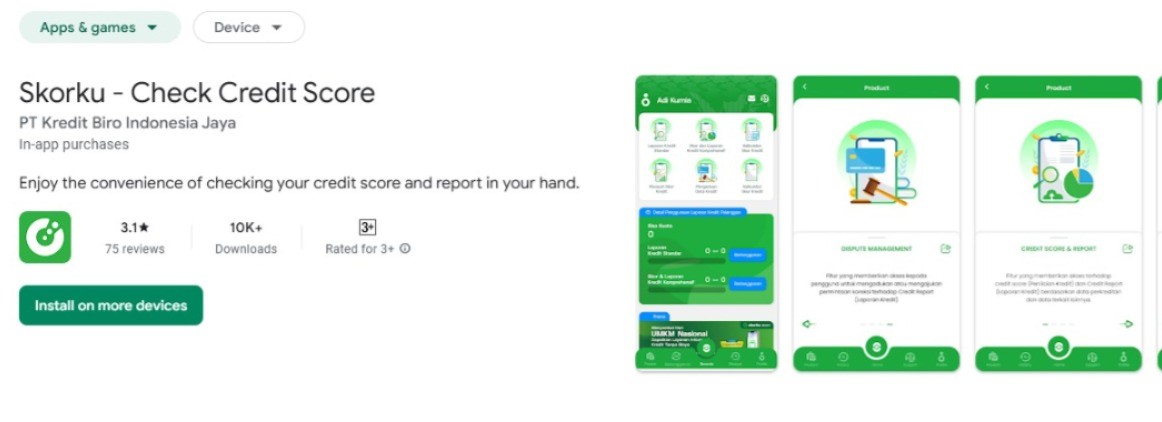
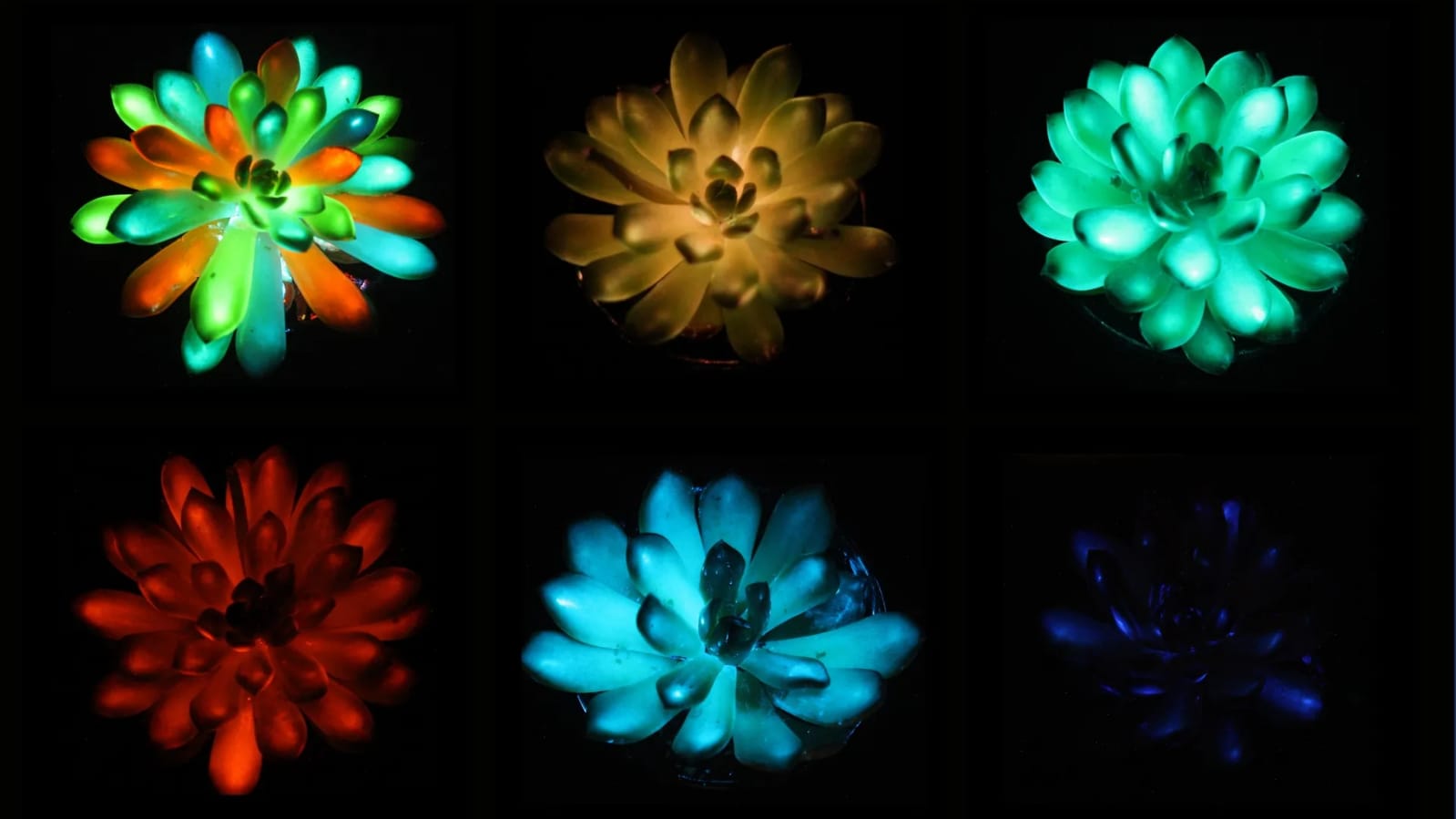
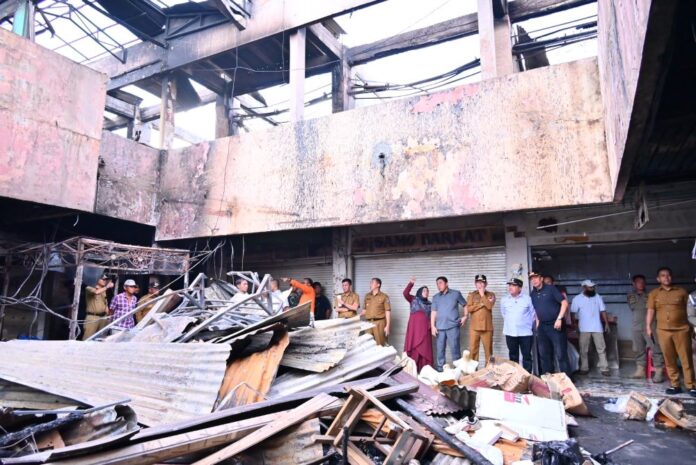



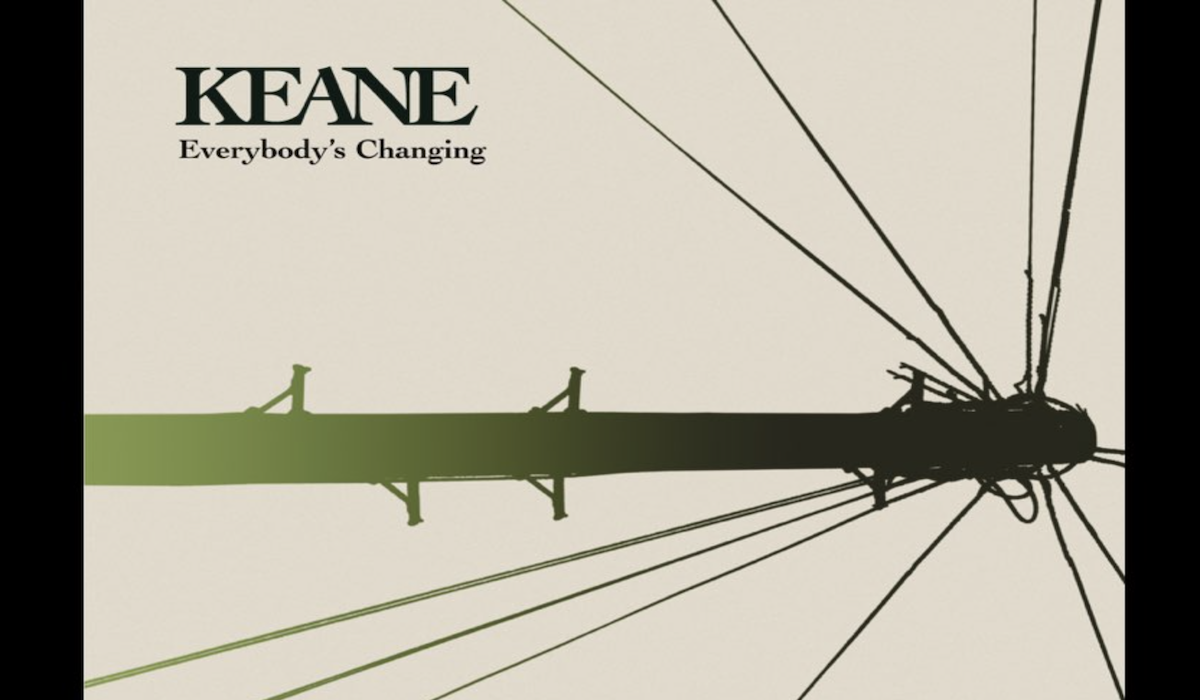
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5248263/original/008680500_1749571851-macOS_Tahoe_26_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·